Hidup terus bergerak karena selalu ada jarak antara harapan dan kenyataan.
Sejak abad ke-5 sebelum masehi Plato 'bermimpi' tentang sebuah negara yang dipimpin oleh seorang filosof. Seorang kepala negara yang lulus dari perkaderan panjang dalam sebuah masyarakat sosialis; dari pembentukan fisik, 'install' pengetahuan, eksperimentasi bergulat dalam masyarakat sampai dengan penanaman-pemuaian kearifan-kearifan. Seorang pemimpin yang sudah selesai berproses dari terminal ke terminal yang sulit sehingga tidak memiliki pamrih untuk pribadi. Ia hidup, berpikir dan berangan-angan hanya semata untuk masyarakat-nya. Negara Plato memang indah untuk dibayangkan. Negara yang dinamakannya: Jumhuriya.
Al-Farabi 'bermimpi' lebih jauh. Negara yang disebutnya 'al-Madinah al-Fadlilah' (negara utama) mesti dipimpin oleh seorang filisof yang memiliki juga kualitas kenabian. Baginya persamaannya adalah Filosof=Nabi. Iya, seorang pemimpin yang tidak hanya melambangkan pucuk struktur sosial kasat mata tetapi juga pucuk kualitas kepemikiran yang mengantarkannya di batas tertinggi kemampuan manusia untuk sampai pada serial mata rantai 'faidl', emanasi yang mesti dilalui seluruh alam semesta untuk sampai ke dunia nyata.
Gambaran-gambaran ini memang lebih asyik digambarkan di alam ide ketimbang ditemukan di alam nyata. Namun sekali lagi, itulah yang menjadikan hidup terus bergerak. Itulah yang menjadikan para pemilik ilmu dan kearifan terus berada dalam pergulatan dengan kekuasaan.
Tahun lalu, Aku sempat pergi ke Iran. Satu hal yang bagiku paling mengesankan di negeri ini adalah ulama-nya yang begitu ber-power. Ulama-lah yang menentukan merah-hitam negeri itu. Namun begitu, bangsa Iran (syiah-nya) masih menunggu Imam Mahdi, sang ratu adil yang menjadi ideal mereka. Maka hidup terus bergerak mengejar idealitasnya.
Selebihnya di banyak negara, para pemilik ilmu (ulama, ilmuan, intelektual) terus begulat dan berbagai formula dengan kekuasaan. Kenapa?. Karena mereka memanggul amanat untuk menggiring masyarakatnya menuju idealitas-idealitas.
Dalam apapun bentuk penampakan dan penggunaan kekuasaan, Intelektual selalu muncul: mengafirmasi, menyediakan perangkat justifikasi, mengkritisi atau menolak dan memberontak.
Samuel P. Huntington muncul untuk 'mengompori' benturan-benturan besar yang terjadi di dunia kita sekarang. Kabarnya, Einstein menyesal menemukan bom atom yang digunakan pada perang dunia II dan menyisakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Antonio Gramsci berbicara tentang dua jenis Intelektual: Tradisional dan Organik untuk menyatakan dengan yang kedua keharusan kaum intelektual untuk terlibat aktif dalam perubahan masyarakatnya.
Tapi kemarin pagi, Aku membaca tulisan Hasyim Shalih di kolom opini Koran as-Syarqul Awsath yang mengulas dengan memikat apa yang disebutnya "intelektual kritis". Makhluk apalagi ini? Menurutnya, kaum intelektual tidak cukup hanya terlibat kemana arah masyarakat bergerak, tetapi lebi dari itu mengkritisi diri masyarakatnya untuk menampakkan penyakit diri sendiri agar tidak terus semakin karam dalam kesalahan yang dimamah biak dari generasi ke generasi. Ia menunjuk konflik Arab-Israel yang berkepanjangan dan tidak menemukan penyelesaian oleh sebab kelompok besar dari kedua belah pihak (termasuk kaum intelektual) masih tidak bisa mengakui eksistensi pihak lain dan tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri. Di sinilah, menurutnya peran penting kaum intlektual kritis untuk melawan arus besar masyakatnya demi masa depan yang lebih baik.
Aku belum paham persis apakah jenis intelektual kritis ini ada di masyarakat kita di Indonesia. Tren yang saya lihat adalah para intelektual ramai-ramai terlibat di partai, birokrasi, kampus atau organisasi keagamaan-kemasyarakat untuk menjadi bagi yang menyusun konsepnya atau menjadi pelaku konsep itu sekalian. Aku belum melihat munculnya kaum intelektual yang serius dan konsisten menjadi bagian yang mengkritisi kesalahan-kesalahan kaprah yang dianggap sebagai 'recieved ideas' di masyarakatnya dan menyusun masa depan masyarakatnya atas basis keilmuan, peradaban dan kearifan yang kuat.
Apakah karena masing-masing kita belum bisa melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi jangka pendek kita?. Atau karena memang masyarakat menuntut demikian?. Dan kita pun, kaum intelektual, terjebak mengiyakannya?
Wednesday, November 22, 2006
Monday, November 13, 2006
Seni Merenung
Harun Yahya menulis buku "Seni Merenung". Aku membaca versi Arab-nya berjudul "Fan at-Taammul".
Kalau pembaca buku ini jujur maka ia pasti tersentil oleh buku ini. Aku merasakan membacanya seperti minum Sprite di siang bolong saat kehausan, ada tusukan-tusukan kecil yang mengasyikkan di tenggorokan. Buku ini menyisakan tusukan-tusukan kecil di hati untuk membuatnya kembali sadar agar balik ke kebeningan awalnya.
Harun Yahya berbicara tentang laba-laba yang merajut jaringan terkuat di dunia sebagai kediamannya. Ia berbicara tentang nyamuk kecil yang mampu mengepakkan sayapnya dengan amat cepat dan desain yang membuatnya bisa bergerak ke segala arah dengan enteng. Satu desain yang kalau bisa diaplikannya pada teknologi pembuatan helikopter, maka ia akan menjadi amat sangat canggih.
Harun Yahya masih berbicara tentang banyak obyek lain yang sangat kita akrabi sebagai tema perenungan. Segala sesuatu, sebenarnya, kalau direnungkan, akan mengantarkan seseorang kepada penciptanya. Mengakui kemahabesaran-Nya dan mensyukuri karunia-karunia-Nya.
Aku jadi teringat dengan Ibnu Rusyd yang mengajukan teori 'ibda' (kreasi) sebagai perangkat argumentatif untuk membuktikan adanya Tuhan. Sebuah teori yang dengan memikat dijelaskan oleh Nadim al-Jisr dalam buku "Qisshat al-Iman"-nya.
Segala keteraturan, kedetailan, kecanggihan, keindahan, guna, yang terdapat pada segala makhluk di cakrawala ini dan relasi indah yang tertaut diantara mereka, tidak bakal ada tiba-tiba tanpa ada yang mengadakan dan mengaturnya. Dengan melongok ke dalam organ jasmaninya saja, seseorang yang jujur dan pintar merenung, pasti sampai pada Tuhan-nya. Maka biasanya, para ilmuan yang jujur pada ujungnya tidak kuasa untuk tidak mengakui ada kekuasaan luar biasa yang mengatur kerumitan, kecanggihan dan ketertataan jagat raya ini. Dan itulah Allah yang esa, berkuasa, penuh kasih, tiada sekutu bagi-Nya.
N.B: Anda bisa membaca karya-karya Harun Yahya di website-nya: www.harunyahya.com
Kalau pembaca buku ini jujur maka ia pasti tersentil oleh buku ini. Aku merasakan membacanya seperti minum Sprite di siang bolong saat kehausan, ada tusukan-tusukan kecil yang mengasyikkan di tenggorokan. Buku ini menyisakan tusukan-tusukan kecil di hati untuk membuatnya kembali sadar agar balik ke kebeningan awalnya.
Harun Yahya berbicara tentang laba-laba yang merajut jaringan terkuat di dunia sebagai kediamannya. Ia berbicara tentang nyamuk kecil yang mampu mengepakkan sayapnya dengan amat cepat dan desain yang membuatnya bisa bergerak ke segala arah dengan enteng. Satu desain yang kalau bisa diaplikannya pada teknologi pembuatan helikopter, maka ia akan menjadi amat sangat canggih.
Harun Yahya masih berbicara tentang banyak obyek lain yang sangat kita akrabi sebagai tema perenungan. Segala sesuatu, sebenarnya, kalau direnungkan, akan mengantarkan seseorang kepada penciptanya. Mengakui kemahabesaran-Nya dan mensyukuri karunia-karunia-Nya.
Aku jadi teringat dengan Ibnu Rusyd yang mengajukan teori 'ibda' (kreasi) sebagai perangkat argumentatif untuk membuktikan adanya Tuhan. Sebuah teori yang dengan memikat dijelaskan oleh Nadim al-Jisr dalam buku "Qisshat al-Iman"-nya.
Segala keteraturan, kedetailan, kecanggihan, keindahan, guna, yang terdapat pada segala makhluk di cakrawala ini dan relasi indah yang tertaut diantara mereka, tidak bakal ada tiba-tiba tanpa ada yang mengadakan dan mengaturnya. Dengan melongok ke dalam organ jasmaninya saja, seseorang yang jujur dan pintar merenung, pasti sampai pada Tuhan-nya. Maka biasanya, para ilmuan yang jujur pada ujungnya tidak kuasa untuk tidak mengakui ada kekuasaan luar biasa yang mengatur kerumitan, kecanggihan dan ketertataan jagat raya ini. Dan itulah Allah yang esa, berkuasa, penuh kasih, tiada sekutu bagi-Nya.
N.B: Anda bisa membaca karya-karya Harun Yahya di website-nya: www.harunyahya.com
Tuesday, November 07, 2006
Karya-karya dari Penjara
Tidak baik menjalani hari-hari yang terlalu bising. Kebisingan sering mengikis kebeningan. Itulah sebabnya, banyak karya besar lahir dari penjara.
Pramoedya melahirkan karya-karya besarnya dari Pulau Buru. Aidl al-Qarni menulis 'La Tahzan'-nya di penjara. Antonio Gramsci matang secara intelektual dari penjara ke penjara. Ibnu Taimiyah melahirkan 'Fatawa'-nya di penjara. Sayyid Qutb menulis Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an-nya, juga, di penjara. Mereka yang hendak melahirkan karya besar, banyak yang memilih 'memenjarakan' diri.
Imam Ghazali mengasingkan diri dari hiruk pikuk Ibu Kota Bagdad untuk kemudian melahirkan 'Ihya Ulumuddin'. Gandi 'memilih' penjara untuk berdialog secara bening dengan batinnya demi menggali hikmah. Lahirlah kemudian konsep-konsep perjuangan anti kekerasan-nya yang memerdekakan Bangsa India. Nadzim al-Jirs mendiktekan 'Qishat al-Iman'-nya di masjid yang 'memenjarakan'-nya untuk total bermunajat dengan Tuhan.
Kebeningan mata batin menjadi barang langka di tengah banjir bandang informasi dan gempita serbuan media di dunia tanpa sekat sekarang ini. Tontotan di layar TV lebih banyak mengeruhkan ketimbang membeningkan. Semboyan hidup dipaksa berubah dari 'al-baqa' lil ashlah' menjadi 'al-baqa' lil asra'. Bintang-bintang palsu di segala bidang terus diciptakan media: merusak dan membingungkan.
Aku jadi ingat Prof.Dr. Said Agil Munawwar. Berkaryalah ustadz! Banyak karya besar lahir dari penjara.
Pramoedya melahirkan karya-karya besarnya dari Pulau Buru. Aidl al-Qarni menulis 'La Tahzan'-nya di penjara. Antonio Gramsci matang secara intelektual dari penjara ke penjara. Ibnu Taimiyah melahirkan 'Fatawa'-nya di penjara. Sayyid Qutb menulis Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an-nya, juga, di penjara. Mereka yang hendak melahirkan karya besar, banyak yang memilih 'memenjarakan' diri.
Imam Ghazali mengasingkan diri dari hiruk pikuk Ibu Kota Bagdad untuk kemudian melahirkan 'Ihya Ulumuddin'. Gandi 'memilih' penjara untuk berdialog secara bening dengan batinnya demi menggali hikmah. Lahirlah kemudian konsep-konsep perjuangan anti kekerasan-nya yang memerdekakan Bangsa India. Nadzim al-Jirs mendiktekan 'Qishat al-Iman'-nya di masjid yang 'memenjarakan'-nya untuk total bermunajat dengan Tuhan.
Kebeningan mata batin menjadi barang langka di tengah banjir bandang informasi dan gempita serbuan media di dunia tanpa sekat sekarang ini. Tontotan di layar TV lebih banyak mengeruhkan ketimbang membeningkan. Semboyan hidup dipaksa berubah dari 'al-baqa' lil ashlah' menjadi 'al-baqa' lil asra'. Bintang-bintang palsu di segala bidang terus diciptakan media: merusak dan membingungkan.
Aku jadi ingat Prof.Dr. Said Agil Munawwar. Berkaryalah ustadz! Banyak karya besar lahir dari penjara.
Monday, November 06, 2006
Iya
Bisakah hidup terus menerus bercahaya? Dulu aku mengandaikannya bisa. Tapi ternyata tidak!
Itulah sebabnya siang berganti malam. Musim berganti dua atau empat kali setahun. Real Madrid mengecewakan dua musim sebelum ini. Barcelona mulai kelihatan jenuh musim ini. Peradaban Islam berjaya di abad pertengahan dan kemudian redup. Amerika pun kini mulai bergerak turun dari puncak.
Hidup memang tidak terus menerus berisi kisah jaya, bergairah, bersemangat, sukses, menang. Hidup juga bakal bertemu kejenuhan, rapuh, stagnan, gelap bahkan lepas kendali.
Lantas kenapa mesti diratapi kalau magrib datang dan sebentar lagi malam menjelang? Kenapa mesti gelisah kalau kejenuhan atau bahkan kegagalan menyapa? Kenapa mesti merasa seolah-olah tidak berguna ketika harapan-harapan tak kesampaian?
Bukankah setiap pergantian hidup mengandung tanda? (atau ayat persisnya). Bukankah malam datang untuk membalut manusia agar beristirahat memberikan hak badan untuk tidak terus berputar?. Agar hidup tertata rapi dan tidak kacau. Tidak baik memaksakan terlalu banyak angan-angan. Angan-angan yang kebanyakan 2/3-nya membuat seseorang menjadi pengecut.
Barangkali ada baiknya, seperti Nietzche, berkata 'iya' untuk segala perubahan apapun yang datang menghampiri.
Itulah sebabnya siang berganti malam. Musim berganti dua atau empat kali setahun. Real Madrid mengecewakan dua musim sebelum ini. Barcelona mulai kelihatan jenuh musim ini. Peradaban Islam berjaya di abad pertengahan dan kemudian redup. Amerika pun kini mulai bergerak turun dari puncak.
Hidup memang tidak terus menerus berisi kisah jaya, bergairah, bersemangat, sukses, menang. Hidup juga bakal bertemu kejenuhan, rapuh, stagnan, gelap bahkan lepas kendali.
Lantas kenapa mesti diratapi kalau magrib datang dan sebentar lagi malam menjelang? Kenapa mesti gelisah kalau kejenuhan atau bahkan kegagalan menyapa? Kenapa mesti merasa seolah-olah tidak berguna ketika harapan-harapan tak kesampaian?
Bukankah setiap pergantian hidup mengandung tanda? (atau ayat persisnya). Bukankah malam datang untuk membalut manusia agar beristirahat memberikan hak badan untuk tidak terus berputar?. Agar hidup tertata rapi dan tidak kacau. Tidak baik memaksakan terlalu banyak angan-angan. Angan-angan yang kebanyakan 2/3-nya membuat seseorang menjadi pengecut.
Barangkali ada baiknya, seperti Nietzche, berkata 'iya' untuk segala perubahan apapun yang datang menghampiri.
Friday, October 27, 2006
Will Durant
Sebuah potret intelektual par exellent. Beliau meninggalkan bekerja mengajar di usia muda. Lantas menseriusi proyek besarnya: Sejarah Peradaban (The Story of Civilization) sampai usia 96 bersama istri tercintanya: ARIEL. Hampir seluruh belahan dunia dikunjunginya. Perhatiannya membentang dari ribuan tahun sebelum masehi pada peradaban timur sampai dengan abad ke-19 masehi di peradaban Eropa modern. Membentang dari sisi ekonomi, militer, kebudayaan, keilmuan, sampai dengan gaya hidup bangsa-bangsa. Seorang lelaki yang menuntaskan pekerjaan yang belum tentu bisa dituntaskan ribuan orang. Ya, Will Durant.
Aku menyukai tulisan-tulisannya. Refleksinya yang jernih dan jujur. Horizonnya yang luas. Pesan kemanusiaannya yang dalam dan abadi. Kita butuh orang macam Will di setiap masa untuk menjadi guru bagi semua.
Aku menyukai tulisan-tulisannya. Refleksinya yang jernih dan jujur. Horizonnya yang luas. Pesan kemanusiaannya yang dalam dan abadi. Kita butuh orang macam Will di setiap masa untuk menjadi guru bagi semua.
Monday, October 23, 2006
Monday, September 25, 2006
Membangun dengan Keteladanan
Sejarah membuktikan bahwa pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan dengan keteladanan.
Saya senang dengan contoh hidup bersahaja yang diberikan beberapa tokoh negeri ini.
Wakil Presiden RI, Bapak Yusuf Kalla, melakukan kunjungan kenegaraan dengan pesawat komersial. Sebelumnya, Ketua MPR, Bapak Hidayat Nur Wahid, menghembuskan spirit hidup bersahaja dengan menolak mobil dinas mewah dan fasilitas berlebihan dalam kunjungannya ke daerah-daerah. Saya juga salut dengan kebersahajaan Dubes RI untuk Kerajaan Maroko, Bapak Sjahwien Adenan.
Keteladanan semacam ini sangat penting menjadi basis kemandirian bangsa dan upaya mensejahterakan rakyat. Sumber keagamaan, peradaban dan filsafat sering menyebut pemimpin sejati sebagai refleksi dari kondisi riil masyarakatnya. Untuk menyebut contoh, Nabi Muhammad, hidup tidak lebih dari cara hidup umatnya yang paling tidak mampu. Tokoh Mahatma Ghandi, India, atau Imam Khomeini, Iran, memilih kesederhanaan sebagai prinsip hidup yang disetiainya. Para pemimpin dan tokoh sepanjang masa membangun kebesarannya tidak dari kemewahan material.
Kata sebuah kearifan, 'mimpi orang biasa adalah untuk dirinya sendiri, tetapi mimpi orang besar adalah untuk orang lain'.
Kalau saja prinsip kebersahajaan ini dimiliki oleh seluruh pemimpin Bangsa Indonesia di semua level, saya kira kesejahteraan untuk semua tidak bakal menunggu terlalu lama untuk menjadi kenyataan.
Semoga saja spirit yang dihembuskan oleh Pak Yusuf Kalla atau Pak Hidayat Nur Wahid bisa menjadi contoh yang baik bagi para elit yang lain.
Saya senang dengan contoh hidup bersahaja yang diberikan beberapa tokoh negeri ini.
Wakil Presiden RI, Bapak Yusuf Kalla, melakukan kunjungan kenegaraan dengan pesawat komersial. Sebelumnya, Ketua MPR, Bapak Hidayat Nur Wahid, menghembuskan spirit hidup bersahaja dengan menolak mobil dinas mewah dan fasilitas berlebihan dalam kunjungannya ke daerah-daerah. Saya juga salut dengan kebersahajaan Dubes RI untuk Kerajaan Maroko, Bapak Sjahwien Adenan.
Keteladanan semacam ini sangat penting menjadi basis kemandirian bangsa dan upaya mensejahterakan rakyat. Sumber keagamaan, peradaban dan filsafat sering menyebut pemimpin sejati sebagai refleksi dari kondisi riil masyarakatnya. Untuk menyebut contoh, Nabi Muhammad, hidup tidak lebih dari cara hidup umatnya yang paling tidak mampu. Tokoh Mahatma Ghandi, India, atau Imam Khomeini, Iran, memilih kesederhanaan sebagai prinsip hidup yang disetiainya. Para pemimpin dan tokoh sepanjang masa membangun kebesarannya tidak dari kemewahan material.
Kata sebuah kearifan, 'mimpi orang biasa adalah untuk dirinya sendiri, tetapi mimpi orang besar adalah untuk orang lain'.
Kalau saja prinsip kebersahajaan ini dimiliki oleh seluruh pemimpin Bangsa Indonesia di semua level, saya kira kesejahteraan untuk semua tidak bakal menunggu terlalu lama untuk menjadi kenyataan.
Semoga saja spirit yang dihembuskan oleh Pak Yusuf Kalla atau Pak Hidayat Nur Wahid bisa menjadi contoh yang baik bagi para elit yang lain.
Sunday, September 24, 2006
Sunday, September 17, 2006
Syarat Kepemimpinan
Kata Qur’an, ada tiga senjata yang Tuhan berikan ke Nabi Dawud untuk menjadi pemimpin: kekuasaan, kearifan dan pengetahuan. Ternyata memang, betapa butuh pemimpin di level manapun terhadap tiga senjata ini.
Pemimpin harus punya kekuasaan, sebab tanpa kekuasaan, suaranya tidak akan didengar. Kekuasaan harus lahir dari legitimasi, sebab tanpa legitimasi, kekuasaan tercerabut dari sukma rakyat.
Kekuasaan harus dibarengi kearifan. Sebab jika tidak, ia akan berubah menjadi sumber petaka. Sumber keserakahan, angkara murka, kezaliman. Kekuasaan tanpa kearifan adalah pedang maha tajam di genggaman raja penyamun.
Lantas, ilmu pengetahuan bertugas menterjemahkan semangat kekuasaan yang dibalut kearifan menjadi kerjanyata mensejahterakan semua.
Pemimpin harus punya kekuasaan, sebab tanpa kekuasaan, suaranya tidak akan didengar. Kekuasaan harus lahir dari legitimasi, sebab tanpa legitimasi, kekuasaan tercerabut dari sukma rakyat.
Kekuasaan harus dibarengi kearifan. Sebab jika tidak, ia akan berubah menjadi sumber petaka. Sumber keserakahan, angkara murka, kezaliman. Kekuasaan tanpa kearifan adalah pedang maha tajam di genggaman raja penyamun.
Lantas, ilmu pengetahuan bertugas menterjemahkan semangat kekuasaan yang dibalut kearifan menjadi kerjanyata mensejahterakan semua.
Wednesday, August 30, 2006
Belajar dari Hizbullah
Sayyid Hasan Nasrullah. Nama ini menjadi buah bibir bangsa Arab-Islam akhir-akhir ini. Ia bukan lagi sekedar tokoh Syiah tetapi telah melompat menjadi simbol perlawanan bangsa Arab terhadap pendudukan Israel dan hegemoni Amerika.
Perang 33 hari itu telah menunjukkan banyak hal. Pertama, citra militer Israel sebagai kekuatan paling besar dan tak terkalahkan di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya runtuh oleh perlawanan heroik milisi Hizbullah. Kedua,proyek "Timur Tengah Raya" Amerika di kawasan ini semakin sulit menyentuh bumi kalau tidak bisa dibilang gagal. Ketiga, terjadi pergeseran aliansi politik dengan setidaknya dua kekuatan besar: Hizbullah-Hamas-Suriah dan Iran di satu pihak dan Yordania-Saudi Arabia dan Mesir di pihak lain. Singkatnya, yang pertama kontra Amerika dan yang kedua pro Amerika.
Hizbullah membuktikan diri bisa melawan Israel (dan Amerika di belakangnya) di semua level: operasi militer, kecanggihan intelijen, payung politik, perang media, kekuatan uang, dukungan opini publik dan --sebagai basis dari semuanya-- kekuatan ideologi.
Awalnya, Hizbullah menawarkan solusi politik untuk pembebasan dua tentara Israel yang ditawannya. Tetapi Israel melihatnya sebagai peluang untuk menghancurkan Hizbullah. Kekuatan militer pun digelar. Targetnya: membebaskan dua tawanan dan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah. Hasilnya: gagal total. Dua sandera tidak berhasil dibebaskan. Kekuatan militer Hizbullah pun masih menjadi ancaman besar buat Israel.
Adu canggih intelijen juga berlaku dalam perang ini. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Hizbullah berhasil menanam perangkat intelijennya yang bekerja dengan sangat rahasia di dalam Israel. Maka seluruh keputusan pergerakan militer : kapan harus melepas rudal, kapan menyergap, kapan mundur, mana saja target sasaran dan seterusnya, dibuat berdasarkan informasi intelijen yang akurat. Sementara itu, beberapa kali, tentara Israel menyerang rumah sakit, pemukiman rakyat dan fasilitas umum yang disangka salah sebagai tempat penyembunyian senjata Hizbullah atau salah menangkap orang hanya karena bernama Hasan Nasrullah. Bukti-bukti gagal-sukses adu kecanggihan perangkat intelijen ini banyak beredar di televisi atau media-media online berbahasa Arab.
Pada tingkat kekuatan politik, Hizbullah juga pandai berhitung. Dua hari setelah Israel menyerang Lebanon, Saudi Arabia justru menyalahkan Hizbullah. Belakangan, Raja Abdullah, Yordania dan Husni Mubarak, Presiden Mesir, menyampaikan suara senada. Hizbullah dianggap nekat dan tanpa perhitungan menawan tentara Israel yang menyebabkan Israel ngamuk dan menyerang Lebanon. Namun ternyata, poros politik ini segera saja mendapat kontra wacananya ketika Suriah dan --terutama-- Iran mendukung Hizbullah. Di tingkat tekanan massa, politik jalanan di Mesir dan Amman mendesakkan suara yang berseberangan dari suara resmi pemerintahnya. Artinya, Hizbullah berhitung juga soal kekuatan politik di tingkat kawasan dan global dalam setiap pergerakannya. Kini, apapun perubahan politik yang hendak dilakukan di kawasan ini, Hizbullah harus diletakkan sebagai salah satu faktor pertimbangan.
Perang urat syaraf dan perebutan opini publik pun berlangsung tidak kalah sengit dalam perang 33 hari ini. Hasan Nasrullah sebagai ikon utama tampil elegan, gagah, cerdas, fasih dan menggugah menyapa publik dan milisi-nya di medan laga secara teratur di layar kaca. Tujuannya: menguatkan mental kawan dan menghancurkan mental lawan. Untuk itu,Televisi Al-Manar, corong resmi Hizbullah, tampil efektif membela kepentingan Hizbullah. Lebih dari itu, televisi Al-Jazeera di Doha dan Al-Alam di Teheran secara kasat mata 'berpihak' kepada Hizbullah dalam perang ini. Dari sisi media, Hizbullah menang besar dalam perang kali ini.
Sebagai efek berantai, masyarakat Arab semakin yakin bahwa muqawamah (gerakan perlawanan terhadap okupasi Israel-Amerika) adalah satu-satunya pilihan yang tersisa dalam konflik panjang Arab-Israel. Label yang diusung oleh Hizbullah dan Hamas dalam pergumulannya dengan Israel. Sebab segala bentuk kesepakatan politik yang ditandatangani dengan Israel, sejauh ini tidak berhasil menghentikan tindakan brutal tentara Israel yang menghancurkan rumah, menangkapi tokoh-tokoh resistensi di Palestina dan tidak ragu menjadikan rakyat sipil tak berdosa sebagai korban meninggal atau luka-luka.
Bagaimana dengan kekuatan uang?. Sejak awal politik Israel-Amerika adalah bagaimana menjauhkan rakyat Lebanon dari Hizbullah. Bahkan, bagaimana membalik opini massa dari mendukung menjadi menolak Hizbullah. Itulah salah satu sebab tentara Israel membombardir rumah-rumah, jembatan, rumah sakit, bandara yang tidak ada sangkut-pautnya dengan gudang senjata Hizbullah. Targetnya, agar massa menyalahkan Hizbullah karena menjadi penyebab semua kehancuran itu. "Kalau saja Hizbullah tidak memancing amuk Israel, niscaya kehancuran ini tidak terjadi", itulah kira-kira yang diharapkan oleh Israel-Amerika muncul di benak rakyat Lebanon.
Maka ketika gencatan sejata dicapai, Amerika mendapat peluang untuk mengambil hati rakyat Lebanon dengan isu rekonstruksi. Namun apa yang terjadi?. Segera setelah gencatan senjata, Hassan Nasrullah tampil di layar kaca dan mengumumkan bahwa : pertama, seluruh keluarga yang mengalami kerugian oleh sebab perang (diperkirakan antara 15-25 ribu keluarga) akan mendapat dana 12.000 Dolar Amerika per keluarga untuk bisa sewa rumah selama setahun. Kedua, Hizbullah akan membangun kembali rumah-rumah yang hancur sesegera mungkin yang diperkirakan berjumlah 15.000 rumah dengan perkiraan anggaran 30.000 Dolar Amerika per rumah. Bisa dibayangkan betapa besar kekuatan dana Hizbullah. Memang muncul banyak spekulasi soal dari mana sumber dana Hizbullah ini. Banyak yang menyebut bahwa sumbernya adalah kombinasi antara sumbangan para dermawan kaya simpatisan Hizbullah di seluruh dunia dan dukungan dana Iran. Tampak di layar kaca, bagaimana para relawan Hizbullah membagi-bagikan uang dalam dolar kepada para keluarga korban untuk biaya hidup setahun.
Kembali kecerdasan politik, kecepatan bertindak dan kekuatan yang memadai bekerja untuk menutup segala peluang yang bisa dipakai oleh kekuatan Israel-Amerika dan para pendukungnya untuk memenangkan pertarungan. Ala kulli hal, Hizbullah yang resminya berdiri tahun 1982, berhasil menjadi kekuatan yang memiliki perangkat militer, politik, intelijen, keuangan, media, hubungan luar dan ideologi yang memadai untuk bermain di level kawasan, membela tanah Lebanon dari segala bentuk agresi dan serobotan Israel.
Apa pelajaran yang tersisa?. Ya, selain sisi militer dan ideologi, organisasi-organasi keagamaan-kemasyarakatan atau bahkan organisasi politik sekalipun, layak berlajar dari Hizbullah. Bagaimana misalnya menjadikan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia bisa kuat dan mandiri secara prinsip keorganisasian, pendanaan dan media, sehingga peran-peran yang diambil bisa lebih signifikan, baik pada level dalam negeri, kawasan maupun internasional. Tampaknya para aktifis organisasi di dalam negeri perlu bekerja lebih keras untuk membangun kemandiriannya pada seluruh level, tentu dengan tetap berada dalam kerangka aturan main yang disepakati bersama. Kalau musuh kasat mata berupa agresor dan penjajah bersenjata sudah menghilang, bukankah musuh berupa kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan global dan keberingasan imperium oligarki kapitalisme internasional lebih jahat dan berbahaya?.
Perang 33 hari itu telah menunjukkan banyak hal. Pertama, citra militer Israel sebagai kekuatan paling besar dan tak terkalahkan di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya runtuh oleh perlawanan heroik milisi Hizbullah. Kedua,proyek "Timur Tengah Raya" Amerika di kawasan ini semakin sulit menyentuh bumi kalau tidak bisa dibilang gagal. Ketiga, terjadi pergeseran aliansi politik dengan setidaknya dua kekuatan besar: Hizbullah-Hamas-Suriah dan Iran di satu pihak dan Yordania-Saudi Arabia dan Mesir di pihak lain. Singkatnya, yang pertama kontra Amerika dan yang kedua pro Amerika.
Hizbullah membuktikan diri bisa melawan Israel (dan Amerika di belakangnya) di semua level: operasi militer, kecanggihan intelijen, payung politik, perang media, kekuatan uang, dukungan opini publik dan --sebagai basis dari semuanya-- kekuatan ideologi.
Awalnya, Hizbullah menawarkan solusi politik untuk pembebasan dua tentara Israel yang ditawannya. Tetapi Israel melihatnya sebagai peluang untuk menghancurkan Hizbullah. Kekuatan militer pun digelar. Targetnya: membebaskan dua tawanan dan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah. Hasilnya: gagal total. Dua sandera tidak berhasil dibebaskan. Kekuatan militer Hizbullah pun masih menjadi ancaman besar buat Israel.
Adu canggih intelijen juga berlaku dalam perang ini. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Hizbullah berhasil menanam perangkat intelijennya yang bekerja dengan sangat rahasia di dalam Israel. Maka seluruh keputusan pergerakan militer : kapan harus melepas rudal, kapan menyergap, kapan mundur, mana saja target sasaran dan seterusnya, dibuat berdasarkan informasi intelijen yang akurat. Sementara itu, beberapa kali, tentara Israel menyerang rumah sakit, pemukiman rakyat dan fasilitas umum yang disangka salah sebagai tempat penyembunyian senjata Hizbullah atau salah menangkap orang hanya karena bernama Hasan Nasrullah. Bukti-bukti gagal-sukses adu kecanggihan perangkat intelijen ini banyak beredar di televisi atau media-media online berbahasa Arab.
Pada tingkat kekuatan politik, Hizbullah juga pandai berhitung. Dua hari setelah Israel menyerang Lebanon, Saudi Arabia justru menyalahkan Hizbullah. Belakangan, Raja Abdullah, Yordania dan Husni Mubarak, Presiden Mesir, menyampaikan suara senada. Hizbullah dianggap nekat dan tanpa perhitungan menawan tentara Israel yang menyebabkan Israel ngamuk dan menyerang Lebanon. Namun ternyata, poros politik ini segera saja mendapat kontra wacananya ketika Suriah dan --terutama-- Iran mendukung Hizbullah. Di tingkat tekanan massa, politik jalanan di Mesir dan Amman mendesakkan suara yang berseberangan dari suara resmi pemerintahnya. Artinya, Hizbullah berhitung juga soal kekuatan politik di tingkat kawasan dan global dalam setiap pergerakannya. Kini, apapun perubahan politik yang hendak dilakukan di kawasan ini, Hizbullah harus diletakkan sebagai salah satu faktor pertimbangan.
Perang urat syaraf dan perebutan opini publik pun berlangsung tidak kalah sengit dalam perang 33 hari ini. Hasan Nasrullah sebagai ikon utama tampil elegan, gagah, cerdas, fasih dan menggugah menyapa publik dan milisi-nya di medan laga secara teratur di layar kaca. Tujuannya: menguatkan mental kawan dan menghancurkan mental lawan. Untuk itu,Televisi Al-Manar, corong resmi Hizbullah, tampil efektif membela kepentingan Hizbullah. Lebih dari itu, televisi Al-Jazeera di Doha dan Al-Alam di Teheran secara kasat mata 'berpihak' kepada Hizbullah dalam perang ini. Dari sisi media, Hizbullah menang besar dalam perang kali ini.
Sebagai efek berantai, masyarakat Arab semakin yakin bahwa muqawamah (gerakan perlawanan terhadap okupasi Israel-Amerika) adalah satu-satunya pilihan yang tersisa dalam konflik panjang Arab-Israel. Label yang diusung oleh Hizbullah dan Hamas dalam pergumulannya dengan Israel. Sebab segala bentuk kesepakatan politik yang ditandatangani dengan Israel, sejauh ini tidak berhasil menghentikan tindakan brutal tentara Israel yang menghancurkan rumah, menangkapi tokoh-tokoh resistensi di Palestina dan tidak ragu menjadikan rakyat sipil tak berdosa sebagai korban meninggal atau luka-luka.
Bagaimana dengan kekuatan uang?. Sejak awal politik Israel-Amerika adalah bagaimana menjauhkan rakyat Lebanon dari Hizbullah. Bahkan, bagaimana membalik opini massa dari mendukung menjadi menolak Hizbullah. Itulah salah satu sebab tentara Israel membombardir rumah-rumah, jembatan, rumah sakit, bandara yang tidak ada sangkut-pautnya dengan gudang senjata Hizbullah. Targetnya, agar massa menyalahkan Hizbullah karena menjadi penyebab semua kehancuran itu. "Kalau saja Hizbullah tidak memancing amuk Israel, niscaya kehancuran ini tidak terjadi", itulah kira-kira yang diharapkan oleh Israel-Amerika muncul di benak rakyat Lebanon.
Maka ketika gencatan sejata dicapai, Amerika mendapat peluang untuk mengambil hati rakyat Lebanon dengan isu rekonstruksi. Namun apa yang terjadi?. Segera setelah gencatan senjata, Hassan Nasrullah tampil di layar kaca dan mengumumkan bahwa : pertama, seluruh keluarga yang mengalami kerugian oleh sebab perang (diperkirakan antara 15-25 ribu keluarga) akan mendapat dana 12.000 Dolar Amerika per keluarga untuk bisa sewa rumah selama setahun. Kedua, Hizbullah akan membangun kembali rumah-rumah yang hancur sesegera mungkin yang diperkirakan berjumlah 15.000 rumah dengan perkiraan anggaran 30.000 Dolar Amerika per rumah. Bisa dibayangkan betapa besar kekuatan dana Hizbullah. Memang muncul banyak spekulasi soal dari mana sumber dana Hizbullah ini. Banyak yang menyebut bahwa sumbernya adalah kombinasi antara sumbangan para dermawan kaya simpatisan Hizbullah di seluruh dunia dan dukungan dana Iran. Tampak di layar kaca, bagaimana para relawan Hizbullah membagi-bagikan uang dalam dolar kepada para keluarga korban untuk biaya hidup setahun.
Kembali kecerdasan politik, kecepatan bertindak dan kekuatan yang memadai bekerja untuk menutup segala peluang yang bisa dipakai oleh kekuatan Israel-Amerika dan para pendukungnya untuk memenangkan pertarungan. Ala kulli hal, Hizbullah yang resminya berdiri tahun 1982, berhasil menjadi kekuatan yang memiliki perangkat militer, politik, intelijen, keuangan, media, hubungan luar dan ideologi yang memadai untuk bermain di level kawasan, membela tanah Lebanon dari segala bentuk agresi dan serobotan Israel.
Apa pelajaran yang tersisa?. Ya, selain sisi militer dan ideologi, organisasi-organasi keagamaan-kemasyarakatan atau bahkan organisasi politik sekalipun, layak berlajar dari Hizbullah. Bagaimana misalnya menjadikan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia bisa kuat dan mandiri secara prinsip keorganisasian, pendanaan dan media, sehingga peran-peran yang diambil bisa lebih signifikan, baik pada level dalam negeri, kawasan maupun internasional. Tampaknya para aktifis organisasi di dalam negeri perlu bekerja lebih keras untuk membangun kemandiriannya pada seluruh level, tentu dengan tetap berada dalam kerangka aturan main yang disepakati bersama. Kalau musuh kasat mata berupa agresor dan penjajah bersenjata sudah menghilang, bukankah musuh berupa kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan global dan keberingasan imperium oligarki kapitalisme internasional lebih jahat dan berbahaya?.
Monday, July 24, 2006
NU, Pesantren dan Kebangkitan Indonesia
“Standing Ovation” panjang bergemuruh menyertai pengumuman Jonathan Pradana Mailoa sebagai ‘absolutely winner’ pada IPhO (International Physics Olymphiad) ke 37 tahun 2006 di Singapura. Air mata kebanggaan, haru dan bahagia tak kuasa ditahan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Ternyata kita masih memiliki kebanggaan sebagai bangsa. Optimisme masih menemukan tempat di tengah derita bergantian yang menghantam bangsa kita.
Dr. Yohanes Surya,pencetus dan pembimbing Tim Olimpiade Fisika Indonesia, merekam rasa itu di email yang ditulisnya pada 17 Juli 2006 dan beredar di beberapa milis. Rasa kaget dan kagum silih berganti di sampaikan duta-duta besar negara peserta. Dr. Surya menulis, “Selesai upacara, semua orang menyalami. Orang Kazakhtan memeluk erat-erat sambil berkata ”wonderful job...” Orang Malaysia menyalami berkata “You did a great job...” Orang Taiwan bilang :”Now is your turn...” Orang filipina: amazing...” Orang Israel “excellent work...” Orang Portugal:” portugal is great in soccer but has to learn physics from Indonesia”, Orang Nigeria : could you come to Nigeria to train our students too?” Orang Australia: great....” Orang belanda: “you did it!!!” Orang Rusia mengacungkan kedua jempolnya.. Orang Iran memeluk sambil berkata “great wonderful...”. 86 negara mengucapkan selamat”.
Bahkan gaung kemenangan ini bergema sampai ke Eropa. Prof. Marc Deschamps dari Belgia, demikian Dr. Surya, mengirim SMS: “Echo of Indonesian Victory has reached Europe! Congratulations to the champions and their coach for these amazing successes! The future looks bright”. Efek kejut untuk bangkit inilah yang membersitkan fajar kebangkitan Indonesia.
Seperti kata pepatah Cina, “langkah seribu dimulai dari ayunan pertama”. Kita sedang mengayunkan langkah untuk capaian besar. Itulah sebabnya, Dr. Surya memiliki target meraih nobel 2020 dari kerja prestisius ini. Kerja besar dan gila, pada awalnya memang mengundang tawa sinis, namun bersama putaran waktu, sinisme itu terpaksa berubah menjadi decak kagum. Dengan modal potensi besar dan kerja keras, Dr. Surya membuktikan bahwa obsesi-nya itu bukan mimpi.
Yang menarik dicermati adalah efek berantai optimisme ini. Menurut Dr. Surya, prestasi demi prestasi gemilang di pentas kompetisi sains internasional ini telah mendongkrak rasa percaya diri bangsa Indonesia. Bahwa kalau dirawat dengan benar, tunas-tunas bangsa yang berotak cemerlang dapat berperan besar di pentas internasional. Bersamaan dengan itu, gerakan yang dimulai sejak 1993 ini, mulai menemukan bangunan sistemik-nya. Melahirkan fisikawan besar dan basis teori sains bagi kebangkitan Indonesia hanyalah persoalan waktu.
Saat ini, sudah puluhan orang mantan anak didik Dr. Surya sedang menimba ilmu di universitas-universitas ternama Internasional. Di dalam negeri, guru-guru mulai bersemangat meng-up grade diri untuk memperbaiki kapasitas ajarnya dalam sains, terutama fisika. Murid-murid sekolah menengah pun mulai mengapresiasi fisika sebagai pelajaran yang menyenangkan. Intinya, antusiasme, kerja keras dan visi yang jelas adalah kunci meraih sesuatu yang besar.
Expat: jalan pintas ke pentas dunia
Belum lama, suguhan piala dunia sepak bola Jerman 2006 menjadi pusat perhatian dunia. Satu hal menarik yang mesti dicatat, banyak negara-negara kecil di Afrika seperi Pantai Gading, Ghana, Togo, Tunisia bisa tampil dengan kesebelasannya di pentas bergengsi tersebut. Ternyata, sumber daya pesepak bolanya banyak yang bermain di liga-liga Eropa. Sebagai contoh, Didier Drogba (Chelsea) di pantai gading, Essien (Chelsea) di Ghana, Adebayor (Arsenal) di Togo adalah bintang di liga-liga Eropa.
Mengimpor kader-kader potensial ke kandang-kandang penggemblengan paling bermutu di dunia adalah jalan pintas menembus persaingan di dunia global yang semakin datar ini. Mereka akan kembali ke negerinya dengan ilmu, pengalaman, keahlian dan visi ke depan yang cukup untuk membangkitan dan mendayagunakan segala sumber daya di negerinya untuk bangkit mengejar kesetaraan dengan negeri-negeri mentor.
China dan India adalah dua contoh bagus dalam hal ini. Dari pengalaman anak-anak asuh Dr. Surya, terbukti yang selalu menjadi saingan mereka di Universitas-universitas besar di Amerika adalah anak-anak Cina. Mereka inilah yang kemudian menjadi mesin SDM Cina memutar mesin besar kebangkitan ekonomi-nya. Kemajuan industri IT (Information Technology) India juga berangkat dari kisah yang sama. Anak-anak India yang handal di bidang IT dari hasil gemblengan di universitas-universitas besar di barat, kembali ke India untuk memutar mesin kebangkitan bangsanya.
Inilah pula yang kita harapkan dari Indonesia. Harus ada strategi nasional untuk mengikuti alur para expat ini; mulai dari sokongan sejak pembibitan, pengawasan selama pendidikan dan latihan kerja, sampai dengan penyediaan peran-peran signifikan yang bisa mereka ambil dalam kerangka Indonesia bangkit. Inilah jalan pintas memutus lingkaran setan yang menghambat kemajuan Indonesia.
Tentu saja, ini berlaku bukan hanya untuk bidang sains. Tetapi bidang-bidang lain di luar itu; seni, filsafat, sastra, kebudayaan, humaniora, sosial, politik dan seterusnya bisa diletakkan pada alur yang sama. Betapapun kontroversialnya Pramoedya Ananta Toer, karya-karyanya yang diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia adalah kebanggaan Indonesia. Syamsi Ali yang belum lama dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di New York City adalah juga contoh bagus. Intinya, standar karya anak bangsa harus dinaikkan sampai level internasional.
Peran NU dan Pesantren
Tetap menjadi kebanggan menyebut ulama-ulama besar dengan karya monumental di level internasional (dunia Islam) seperti Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfudz Termas, Syekh Yasin Padang, Syekh Arsyad Banjar dan seterusnya. Tapi itu dulu. Ketika jaringan ulama masih memusat di Hijaz dan antusiasme pelajar nusantara belajar ilmu agama masih tinggi.
Ketika pusat itu bergeser ke Mesir, ulama-ulama besar sekaliber mereka, belum muncul lagi sampai hari ini. Kita bisa menyebut Gus Dur atau Gus Mus sebagai generasi mahasiswa Universitas al-Azhar Mesir tahun 60-an, tetapi dengan karya keilmuan yang masih miskin untuk ukuran ulama berkaliber internasional. Begitu juga dengan Quraish Shihab. Meski banyak karya tafsir yang lahir dari tangan beliau, tetap saja belum menembus level dunia untuk bersanding misalnya dengan karya Thahir Bin Asyur atau (sekarang ini) Sayyid Thantawi Grand Syekh Azhar, Syekh Ali Jum’ah, Mufti Mesir atau Syekh Yusuf al-Qardlawi.
Kini kita harap-harap cemas menantikan terobosan dari lumbungnya para kiai: NU dan Pesantren. Sejak generasi Kiai-kiai besar yang wafat pada tahun 90-an awal semisal KH. Ali Maksum, KH. Asad, KH. Ahmad Siddiq, Kiai Adlan Ali, belum muncul secara sistemik dan massif kiai-kiai baru yang komprehensif, kharismatik, mumpuni secara keilmuan dan meninggalkan pengaruh besar.
Kalau boleh mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan Dr. Surya : ambillah bibit unggul dari belasan ribu pesantren se Indonesia, seleksi mereka seketat mungkin, ambil yang paling potensial, godok siang malam, terapkan standar mujtahid (hafal qur’an, matan hadits, ilmu ushul, ilmu alat dan penguasaan terhadap realitas; ditambah (versi Prof. Arkoun) dengan pengetahuan terhadap produk terbaru di dunia ilmu humaniora), wajibkan berbahasa Arab, Inggris (kalau bisa, ditambah Perancis). Ketika dasarnya cukup, kirim mereka ke universitas agama paling berkualitas dan sambungkan mereka dengan syekh yang paling berkualitas juga untuk berlajar dari mereka sampai tuntas. Untuk ini, ambil dana umat karena mereka, selepas dididik, akan bekerja untuk umat.
Dengan antusiasme dan kerja keras segalanya bisa direngkuh. Alangkah membanggakan kalau tidak lama kemudian, secara sistemik, mujtahid-mujtahid muashir muncul dari dunia pesantren dan NU. Ayo NU, ayo Pesantren mulailah lebih serius mempersiapkan mujtahid-mujtahid itu!. Agar suatu saat nanti, Indonesia berhak berada di pusat peradaban manusia. Bukankah langkah seribu dimulai dari langkah pertama?.
Dr. Yohanes Surya,pencetus dan pembimbing Tim Olimpiade Fisika Indonesia, merekam rasa itu di email yang ditulisnya pada 17 Juli 2006 dan beredar di beberapa milis. Rasa kaget dan kagum silih berganti di sampaikan duta-duta besar negara peserta. Dr. Surya menulis, “Selesai upacara, semua orang menyalami. Orang Kazakhtan memeluk erat-erat sambil berkata ”wonderful job...” Orang Malaysia menyalami berkata “You did a great job...” Orang Taiwan bilang :”Now is your turn...” Orang filipina: amazing...” Orang Israel “excellent work...” Orang Portugal:” portugal is great in soccer but has to learn physics from Indonesia”, Orang Nigeria : could you come to Nigeria to train our students too?” Orang Australia: great....” Orang belanda: “you did it!!!” Orang Rusia mengacungkan kedua jempolnya.. Orang Iran memeluk sambil berkata “great wonderful...”. 86 negara mengucapkan selamat”.
Bahkan gaung kemenangan ini bergema sampai ke Eropa. Prof. Marc Deschamps dari Belgia, demikian Dr. Surya, mengirim SMS: “Echo of Indonesian Victory has reached Europe! Congratulations to the champions and their coach for these amazing successes! The future looks bright”. Efek kejut untuk bangkit inilah yang membersitkan fajar kebangkitan Indonesia.
Seperti kata pepatah Cina, “langkah seribu dimulai dari ayunan pertama”. Kita sedang mengayunkan langkah untuk capaian besar. Itulah sebabnya, Dr. Surya memiliki target meraih nobel 2020 dari kerja prestisius ini. Kerja besar dan gila, pada awalnya memang mengundang tawa sinis, namun bersama putaran waktu, sinisme itu terpaksa berubah menjadi decak kagum. Dengan modal potensi besar dan kerja keras, Dr. Surya membuktikan bahwa obsesi-nya itu bukan mimpi.
Yang menarik dicermati adalah efek berantai optimisme ini. Menurut Dr. Surya, prestasi demi prestasi gemilang di pentas kompetisi sains internasional ini telah mendongkrak rasa percaya diri bangsa Indonesia. Bahwa kalau dirawat dengan benar, tunas-tunas bangsa yang berotak cemerlang dapat berperan besar di pentas internasional. Bersamaan dengan itu, gerakan yang dimulai sejak 1993 ini, mulai menemukan bangunan sistemik-nya. Melahirkan fisikawan besar dan basis teori sains bagi kebangkitan Indonesia hanyalah persoalan waktu.
Saat ini, sudah puluhan orang mantan anak didik Dr. Surya sedang menimba ilmu di universitas-universitas ternama Internasional. Di dalam negeri, guru-guru mulai bersemangat meng-up grade diri untuk memperbaiki kapasitas ajarnya dalam sains, terutama fisika. Murid-murid sekolah menengah pun mulai mengapresiasi fisika sebagai pelajaran yang menyenangkan. Intinya, antusiasme, kerja keras dan visi yang jelas adalah kunci meraih sesuatu yang besar.
Expat: jalan pintas ke pentas dunia
Belum lama, suguhan piala dunia sepak bola Jerman 2006 menjadi pusat perhatian dunia. Satu hal menarik yang mesti dicatat, banyak negara-negara kecil di Afrika seperi Pantai Gading, Ghana, Togo, Tunisia bisa tampil dengan kesebelasannya di pentas bergengsi tersebut. Ternyata, sumber daya pesepak bolanya banyak yang bermain di liga-liga Eropa. Sebagai contoh, Didier Drogba (Chelsea) di pantai gading, Essien (Chelsea) di Ghana, Adebayor (Arsenal) di Togo adalah bintang di liga-liga Eropa.
Mengimpor kader-kader potensial ke kandang-kandang penggemblengan paling bermutu di dunia adalah jalan pintas menembus persaingan di dunia global yang semakin datar ini. Mereka akan kembali ke negerinya dengan ilmu, pengalaman, keahlian dan visi ke depan yang cukup untuk membangkitan dan mendayagunakan segala sumber daya di negerinya untuk bangkit mengejar kesetaraan dengan negeri-negeri mentor.
China dan India adalah dua contoh bagus dalam hal ini. Dari pengalaman anak-anak asuh Dr. Surya, terbukti yang selalu menjadi saingan mereka di Universitas-universitas besar di Amerika adalah anak-anak Cina. Mereka inilah yang kemudian menjadi mesin SDM Cina memutar mesin besar kebangkitan ekonomi-nya. Kemajuan industri IT (Information Technology) India juga berangkat dari kisah yang sama. Anak-anak India yang handal di bidang IT dari hasil gemblengan di universitas-universitas besar di barat, kembali ke India untuk memutar mesin kebangkitan bangsanya.
Inilah pula yang kita harapkan dari Indonesia. Harus ada strategi nasional untuk mengikuti alur para expat ini; mulai dari sokongan sejak pembibitan, pengawasan selama pendidikan dan latihan kerja, sampai dengan penyediaan peran-peran signifikan yang bisa mereka ambil dalam kerangka Indonesia bangkit. Inilah jalan pintas memutus lingkaran setan yang menghambat kemajuan Indonesia.
Tentu saja, ini berlaku bukan hanya untuk bidang sains. Tetapi bidang-bidang lain di luar itu; seni, filsafat, sastra, kebudayaan, humaniora, sosial, politik dan seterusnya bisa diletakkan pada alur yang sama. Betapapun kontroversialnya Pramoedya Ananta Toer, karya-karyanya yang diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia adalah kebanggaan Indonesia. Syamsi Ali yang belum lama dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di New York City adalah juga contoh bagus. Intinya, standar karya anak bangsa harus dinaikkan sampai level internasional.
Peran NU dan Pesantren
Tetap menjadi kebanggan menyebut ulama-ulama besar dengan karya monumental di level internasional (dunia Islam) seperti Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfudz Termas, Syekh Yasin Padang, Syekh Arsyad Banjar dan seterusnya. Tapi itu dulu. Ketika jaringan ulama masih memusat di Hijaz dan antusiasme pelajar nusantara belajar ilmu agama masih tinggi.
Ketika pusat itu bergeser ke Mesir, ulama-ulama besar sekaliber mereka, belum muncul lagi sampai hari ini. Kita bisa menyebut Gus Dur atau Gus Mus sebagai generasi mahasiswa Universitas al-Azhar Mesir tahun 60-an, tetapi dengan karya keilmuan yang masih miskin untuk ukuran ulama berkaliber internasional. Begitu juga dengan Quraish Shihab. Meski banyak karya tafsir yang lahir dari tangan beliau, tetap saja belum menembus level dunia untuk bersanding misalnya dengan karya Thahir Bin Asyur atau (sekarang ini) Sayyid Thantawi Grand Syekh Azhar, Syekh Ali Jum’ah, Mufti Mesir atau Syekh Yusuf al-Qardlawi.
Kini kita harap-harap cemas menantikan terobosan dari lumbungnya para kiai: NU dan Pesantren. Sejak generasi Kiai-kiai besar yang wafat pada tahun 90-an awal semisal KH. Ali Maksum, KH. Asad, KH. Ahmad Siddiq, Kiai Adlan Ali, belum muncul secara sistemik dan massif kiai-kiai baru yang komprehensif, kharismatik, mumpuni secara keilmuan dan meninggalkan pengaruh besar.
Kalau boleh mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan Dr. Surya : ambillah bibit unggul dari belasan ribu pesantren se Indonesia, seleksi mereka seketat mungkin, ambil yang paling potensial, godok siang malam, terapkan standar mujtahid (hafal qur’an, matan hadits, ilmu ushul, ilmu alat dan penguasaan terhadap realitas; ditambah (versi Prof. Arkoun) dengan pengetahuan terhadap produk terbaru di dunia ilmu humaniora), wajibkan berbahasa Arab, Inggris (kalau bisa, ditambah Perancis). Ketika dasarnya cukup, kirim mereka ke universitas agama paling berkualitas dan sambungkan mereka dengan syekh yang paling berkualitas juga untuk berlajar dari mereka sampai tuntas. Untuk ini, ambil dana umat karena mereka, selepas dididik, akan bekerja untuk umat.
Dengan antusiasme dan kerja keras segalanya bisa direngkuh. Alangkah membanggakan kalau tidak lama kemudian, secara sistemik, mujtahid-mujtahid muashir muncul dari dunia pesantren dan NU. Ayo NU, ayo Pesantren mulailah lebih serius mempersiapkan mujtahid-mujtahid itu!. Agar suatu saat nanti, Indonesia berhak berada di pusat peradaban manusia. Bukankah langkah seribu dimulai dari langkah pertama?.
Thursday, June 22, 2006
Arabic Contemporary Thinkers (1) : Dr. Thaha Abdurrahman
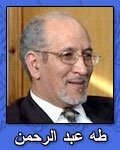
If you have an interest in arabic-islamic thought, I recommend you to visit this site or follow it every monday at 16.30 GMT in aljazeera tv channel in the program called 'masaaraat'. You'll find that it is interesting to see the contemporary Arabic-Islamic Thinkers talk about their thoughts and intelectual projects. Dr. Thaha Abdurrahman, lecturer of logic and linguistic in Mohamed V University in Rabat, is one of them.
Dr. Thaha is named as one of the most creative thinkers in the field of Arabic-Islamic comtemporary thought. His prime intelectual project is the construction of Islamic solution to the problems of this age. His good mastery on logic and linguistic allows him to create some new concepts based on Arabic-Islamic heritage. He proposes, for example, the concepts like 'at-tarjamah at-ta'shiliyah' (the creative translation of greek or modern european philosophy to Arabic), 'al-falsafah al-hiwariyah' (dialogue philosophy), 'al-hadatsah al-islamiyah' (Islamic modernity)etc.
He wrote some books in order to give deep explanation about these concepts, such as 'su'al al-akhlaq', 'al-haq al-islami fi al-ikhtilaf al-fikri', 'ruh al-hadatsah', etc. Unfortunately, all of his books are still in Arabic languange. It will be better if these books were translated into english so they could be accessed by more people.
Wednesday, June 21, 2006
ICIS II: Merubah Elit Sebelum Merubah Massa
APAKAH artinya pertemuan para intelektual muslim di tengah dunia Islam yang sedang bergolak di hadapan kita?.
Irak masih diduduki Amerika dan sekutunya. Faksi Hamas dan Fatah bertikai di Palestina. Somalia masih jadi arena perang saudara. Ketegangan Siria dan Lebanon pasca kematian Rafiq al-Hariri belum juga reda. Uni Emirat Arab dan Iran masih berebut daerah sengketa. Maroko dan Aljazair masih berebut pengaruh di Sahara. Afganistan masih jadi ladang pertempuran pasukan Taliban dan tentara Amerika.
Mauritania jatuh bangun dengan kudeta. Saudi Arabia, Jordania dan Maroko masih di bawah kekuasaan para raja. Mesir masih memberlakukan hukum gawat darurat di bawah kekuasaan Presiden Husni Mubarak yang perkasa. Sudan belum lagi sembuh dari luka perang saudara. Qatar well come saja jadi pangkalan Amerika di perang teluk ketiga yang merontokkan rezim Saddam Hussein yang kini masih dipenjara.
Memang Abu Mus’ab az-Zarqawi sudah tiada. “Patah satu tumbuh seribu”, kata pribahasa. Selama ketidakadilan masih ada, mereka akan terus bekerja dengan ideologi yang kuat bagai baja. Jangan heran jika besok lusa, berita kematin dan kehancuran yang mengerikan masih mengoyak rasa kemanusiaan kita. Osama Benladen dan Aiman az-Zawahiri boleh timbul tenggelam di layar kaca, namun anak-anak muda yang terkena racun ideologinya siap jadi martir hidup kapan saja dan di mana saja, ---sebagaimana yang sudah pernah ada-- dari Inggris hingga Amerika, dari Jakarta hingga Casablanca.
Laporan UNDP tahun 2002, rata-rata pertumbahan perkapita di negeri-negeri Arab hanya 1 % per tahun sepanjang 20 tahun sebelumnya. Dua dari lima orang Arab, hidup per hari hanya dengan kurang dari 2 dolar Amerika. 15 % kekuatan kerja di negeri-negeri Arab tidak bekerja dan pada tahun 2010 diperkirakan berlipat dua. Hanya ada 1 % penduduk yang memiliki komputer pribadi dan hanya setengah persen yang tersambung di jagat maya. Separuh dari perempuan Arab tidak bisa membaca.
Kalau ke Sudan kita mengarahkan mata, ada Darfur yang menjadi arena tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Konflik, kelaparan dan orang-orang yang tinggal di pengungsian menjadi pemandangan sehari-hari di sana. Laporan PBB menyebutkan, dalam rentang 1994-2003, ada 13 juta orang mati karena konflik, 12 juta-nya ada di kawasan Asia Barat, Asia Selatan dan Sub Sahara Afrika. ¾ dari 37 juta pengungsi juga berada di kawasan ini, berkelindan dengan angka kelaparan yang naik tangga.
Bagaimana dengan negeri kita?. Kabar baik berhembus bersama reformasi, Mei 1998, yang didesakkan massa dan mahasiswa. Momentum ini membawa perubahan mendasar berupa: demokrasi dengan pemilihan langsung, amandemen UUD 1945 dan desentralisasi kekuasaan ke pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Namun, 26 Desember 2004, tsunami menghantam Aceh dan Nias, meminta korban hampir 200 ribu jiwa dan kerja rekonstruksi yang luar biasa. Luka masih menganga ditinggalkan oleh Jogja yang dihantam gempa.
Atas alasan inilah, katanya, pemerintah berhutang lagi untuk kesekian kalinya. Hutang yang menambah beban yang harus dibayar oleh anak cucu bangsa. Sementara pengangguran sudah mencapai angka 40 juta jiwa. Flu burung masih juga mengancam jiwa dan sedang diusahakan solusi tuntasnya. Anak-anak kurang gizi masih ada dan pernah ramai jadi berita. Pemaksaan kehendak dengan kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu mengancam integrasi bangsa.
DALAM kondisi dunia Islam macam inilah, para intelektual dari 57 negara berbasis muslim berkumpul di Jakarta. Banyak yang diharapkan dari mereka. Setidaknya, kalau elit berubah, massa pasti mengikutinya. Revolusi di tingkat elit, akan sangat menentukan revolusi di tingkat massa.
Tetapi bagaimana itu bisa?. Bagaimana ilustrasinya?. Mohamed Arkoun, Profesor di Universitas Sorbon Perancis, menuntut intlektual Islam untuk membuka diri dan menguasai produk terbaru di dunia ilmu-ilmu humaniora. Hanya dengan begitu, peradaban Islam akan kembali ke peran kesejarahannya. Arkoun mengambil inspirasi dari para intelektual abad ke-4 H semisal Abu Hayyan at-Tauhidi dan Ibnu Maskawaih yang lengkap, terbuka, menyerap segala produk peradaban di zamannya dan memberi kontribusi dunia Islam bagi kemajuan dunia manusia. Arkoun meminta intelektual Islam mengadopsi peran Maskawaih di zamannya dalam konteks zaman kita. Dalam hal ini, Arkoun mencoba mengambil peran pelopor dengan karya-karyanya yang dalam, multi perangkat metodologis dan menggebrak imaginasi kolektif umat yang menurutnya sudah kadung ideologis, berwatak keras dan tidak terbuka.
Dalam semangat mencari jawaban Islam terhadap kebuntuan zaman kita, Dr. Abu Ya’rab al-Marzuqi, intelektual Tunisia, menemukannya pada Ibnu Taymiyah dan Ibnu Khaldun setelah menemukan titik terang pada al-Gazali, tokoh intelektual Islam abad V. Al-Marzuqi menemukan persamaan “Ihya’ Ulumuddin”-nya al-Gazali sama dengan “Ihya al-Hadlarah al-Islamiyah” karena pada masa itu, filsafat sejarah Plato dan filsafat ilmu alam Aristoteles telah menyebabkan kematian ilmu agama yang berarti kematian manusia. Karena manusia –versi Plato dan Aristoteles—digerakkan oleh sejarah dan hukum alam (hukum kausalitas), bukan sebaliknya.
Ibnu Taymiyah dan Ibnu Khaldun, menurut Abu Ya’rab al-Marzuqi, membalik kesimpulan Plato dan Aristoteles (yang diafirmasi oleh intelektual Islam semacam: Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, As-Suhrawardi dan Ibnu Rusyd) untuk mengembalikan posisi manusia sebagai penggerak (fa’il) sejarah yang merdeka, bukan obyek (maf’ul) sejarah. Menggerakkan reformasi di dunia Islam saat ini, menurut al-Marzuqi, harus dilandaskan pada dua poros pemikiran ini: 1. terbebas dari metafisika jabariyah yang memandang manusia sebagai entitas yang digerakkan oleh kekuatan luar yang tak tertolak; 2. terbebas dari sikap tidak bertanggung jawab yang diakibatkan oleh pandangan bahwa nilai-nilai bukan ditimbulkan oleh kerja manusia yang muncul dari pergulatan kekuatan di masyarakat tetapi dari Tuhan yang segalanya serba jadi tanpa keterlibatan perjuangan dan kreasi manusia. Poros pertama memerdekakan manusia secara teologis, menjadikannya sebagai entitas yang berkehendak dan bertanggung jawab ; dan yang kedua memerdekakan manusia secara sosial-politis dari otoritarianisme masyarakat dan negara.
Dr. Thaha Abdurrahman, pemikir Maroko, melangkah lebih jauh. Dalam buku terbarunya, “Ruh al-Hadatsah; al-Madkhal ila Ta’sis al-Hadatsah al-Islmiyah” (2006), ia mengajukan konsep yang disebutnya dengan modernitas Islam. Konsep ini dialamatkannya kepada dua kelompok sekaligus; 1. para intelektual yang hanya mencukupkan diri dengan tradisi (turastiyyun) untuk mengajukan kepada mereka cakrawala baru, dan, 2. para intelektual modernis (hadatsiyyun) yang hanya menjadi pengikut setia modernitas barat untuk memberi mereka alternatif dari kenyataan modernitas barat yang penuh kritik.
Dr. Thaha membedakan antara “ruh modernitas” dan “kenyataan (penerapan) modernitas”. Menurutnya, modernitas barat saat ini adalah salah satu bentuk penerapan ruh modernitas yang dimungkinkan. Artinya, sangat mungkin menerapkan ruh modernitas ini di dunia Islam dalam perangkat dan bentuk yang lebih mencerminkan ruh tersebut. Tiga prinsip modernitas: prinsip kritik (mabda’ an-naqd), prinsip kearifan (mabda’ ar-rusyd) dan prinsip totalitas (mabda’ as-syumul) yang merupakan ruh modernitas dibebernya dalam bahasa dan konsep-konsep yang sepenuhnya diturunkannya dari sumber dan warisan pemikiran Islam. Pertaruhannya kemudian adalah bagaimana memperjuangkan kondisi dunia Islam yang diisi oleh perpaduan kebangkrutan intern dan luberan eksternal (modernitas barat) beranjak menuju aplikasi konsep yang dikreasinya. Setidaknya, Dr. Thaha sudah memberikan track konsepnya.
Dalam konteks perjuangan menghadapi kondisi dunia Islam yang amat berat inilah, Mohamed Abed al-Jabiri menganjurkan jalan keluar yang disebutnya “kaukus sejarah” (at-takattul at-tarikhi) dunia Arab-Islam. Kaukus ini meniscayakan umat Islam berada di satu barisan dengan garis kebijakan sosial-politik-peradaban yang dirumuskan bersama. Al-Jabiri melihat bahwa tantangan dunia Islam jauh lebih besar dari sekedar dihadapi dengan solusi-solusi sektoral. Inilah saatnya umat Islam bersatu dalam satu lingkaran untuk bergerak bangkit bersama. Solusi ini, menurut al-Jabiri, bisa mengembalikan umat Islam kembali menjadi pemain sejarah, tidak seperti kini, ketika dunia Islam menjadi obyek pertarungan (dalam apa yang disebutnya sebagai tata ulang peta dunia oleh Amerika), bukan pihak yang aktif bermain dalam pertarungan tersebut.
APAKAH peran kesejarahan ini hendak dimulai dari Jakarta melalui forum ICIS?. Melihat tren demokrasi yang mulai bersemi, kebebasan bertanggung jawab yang mulai nyata dan semangat menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, ICIS ----dengan PBNU sebagai markasnya-- bisa menjadi tonggak sejarah untuk memulai perubahan serius (kalau bukan revolusi) di dunia Islam. Asal semangatnya besar dan tujuannya jelas, ICIS bisa melakukannya. Perjuangan memang tidak pernah mengenal kata henti, bahkan mungkin baru bermula!.
Irak masih diduduki Amerika dan sekutunya. Faksi Hamas dan Fatah bertikai di Palestina. Somalia masih jadi arena perang saudara. Ketegangan Siria dan Lebanon pasca kematian Rafiq al-Hariri belum juga reda. Uni Emirat Arab dan Iran masih berebut daerah sengketa. Maroko dan Aljazair masih berebut pengaruh di Sahara. Afganistan masih jadi ladang pertempuran pasukan Taliban dan tentara Amerika.
Mauritania jatuh bangun dengan kudeta. Saudi Arabia, Jordania dan Maroko masih di bawah kekuasaan para raja. Mesir masih memberlakukan hukum gawat darurat di bawah kekuasaan Presiden Husni Mubarak yang perkasa. Sudan belum lagi sembuh dari luka perang saudara. Qatar well come saja jadi pangkalan Amerika di perang teluk ketiga yang merontokkan rezim Saddam Hussein yang kini masih dipenjara.
Memang Abu Mus’ab az-Zarqawi sudah tiada. “Patah satu tumbuh seribu”, kata pribahasa. Selama ketidakadilan masih ada, mereka akan terus bekerja dengan ideologi yang kuat bagai baja. Jangan heran jika besok lusa, berita kematin dan kehancuran yang mengerikan masih mengoyak rasa kemanusiaan kita. Osama Benladen dan Aiman az-Zawahiri boleh timbul tenggelam di layar kaca, namun anak-anak muda yang terkena racun ideologinya siap jadi martir hidup kapan saja dan di mana saja, ---sebagaimana yang sudah pernah ada-- dari Inggris hingga Amerika, dari Jakarta hingga Casablanca.
Laporan UNDP tahun 2002, rata-rata pertumbahan perkapita di negeri-negeri Arab hanya 1 % per tahun sepanjang 20 tahun sebelumnya. Dua dari lima orang Arab, hidup per hari hanya dengan kurang dari 2 dolar Amerika. 15 % kekuatan kerja di negeri-negeri Arab tidak bekerja dan pada tahun 2010 diperkirakan berlipat dua. Hanya ada 1 % penduduk yang memiliki komputer pribadi dan hanya setengah persen yang tersambung di jagat maya. Separuh dari perempuan Arab tidak bisa membaca.
Kalau ke Sudan kita mengarahkan mata, ada Darfur yang menjadi arena tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Konflik, kelaparan dan orang-orang yang tinggal di pengungsian menjadi pemandangan sehari-hari di sana. Laporan PBB menyebutkan, dalam rentang 1994-2003, ada 13 juta orang mati karena konflik, 12 juta-nya ada di kawasan Asia Barat, Asia Selatan dan Sub Sahara Afrika. ¾ dari 37 juta pengungsi juga berada di kawasan ini, berkelindan dengan angka kelaparan yang naik tangga.
Bagaimana dengan negeri kita?. Kabar baik berhembus bersama reformasi, Mei 1998, yang didesakkan massa dan mahasiswa. Momentum ini membawa perubahan mendasar berupa: demokrasi dengan pemilihan langsung, amandemen UUD 1945 dan desentralisasi kekuasaan ke pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Namun, 26 Desember 2004, tsunami menghantam Aceh dan Nias, meminta korban hampir 200 ribu jiwa dan kerja rekonstruksi yang luar biasa. Luka masih menganga ditinggalkan oleh Jogja yang dihantam gempa.
Atas alasan inilah, katanya, pemerintah berhutang lagi untuk kesekian kalinya. Hutang yang menambah beban yang harus dibayar oleh anak cucu bangsa. Sementara pengangguran sudah mencapai angka 40 juta jiwa. Flu burung masih juga mengancam jiwa dan sedang diusahakan solusi tuntasnya. Anak-anak kurang gizi masih ada dan pernah ramai jadi berita. Pemaksaan kehendak dengan kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu mengancam integrasi bangsa.
DALAM kondisi dunia Islam macam inilah, para intelektual dari 57 negara berbasis muslim berkumpul di Jakarta. Banyak yang diharapkan dari mereka. Setidaknya, kalau elit berubah, massa pasti mengikutinya. Revolusi di tingkat elit, akan sangat menentukan revolusi di tingkat massa.
Tetapi bagaimana itu bisa?. Bagaimana ilustrasinya?. Mohamed Arkoun, Profesor di Universitas Sorbon Perancis, menuntut intlektual Islam untuk membuka diri dan menguasai produk terbaru di dunia ilmu-ilmu humaniora. Hanya dengan begitu, peradaban Islam akan kembali ke peran kesejarahannya. Arkoun mengambil inspirasi dari para intelektual abad ke-4 H semisal Abu Hayyan at-Tauhidi dan Ibnu Maskawaih yang lengkap, terbuka, menyerap segala produk peradaban di zamannya dan memberi kontribusi dunia Islam bagi kemajuan dunia manusia. Arkoun meminta intelektual Islam mengadopsi peran Maskawaih di zamannya dalam konteks zaman kita. Dalam hal ini, Arkoun mencoba mengambil peran pelopor dengan karya-karyanya yang dalam, multi perangkat metodologis dan menggebrak imaginasi kolektif umat yang menurutnya sudah kadung ideologis, berwatak keras dan tidak terbuka.
Dalam semangat mencari jawaban Islam terhadap kebuntuan zaman kita, Dr. Abu Ya’rab al-Marzuqi, intelektual Tunisia, menemukannya pada Ibnu Taymiyah dan Ibnu Khaldun setelah menemukan titik terang pada al-Gazali, tokoh intelektual Islam abad V. Al-Marzuqi menemukan persamaan “Ihya’ Ulumuddin”-nya al-Gazali sama dengan “Ihya al-Hadlarah al-Islamiyah” karena pada masa itu, filsafat sejarah Plato dan filsafat ilmu alam Aristoteles telah menyebabkan kematian ilmu agama yang berarti kematian manusia. Karena manusia –versi Plato dan Aristoteles—digerakkan oleh sejarah dan hukum alam (hukum kausalitas), bukan sebaliknya.
Ibnu Taymiyah dan Ibnu Khaldun, menurut Abu Ya’rab al-Marzuqi, membalik kesimpulan Plato dan Aristoteles (yang diafirmasi oleh intelektual Islam semacam: Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, As-Suhrawardi dan Ibnu Rusyd) untuk mengembalikan posisi manusia sebagai penggerak (fa’il) sejarah yang merdeka, bukan obyek (maf’ul) sejarah. Menggerakkan reformasi di dunia Islam saat ini, menurut al-Marzuqi, harus dilandaskan pada dua poros pemikiran ini: 1. terbebas dari metafisika jabariyah yang memandang manusia sebagai entitas yang digerakkan oleh kekuatan luar yang tak tertolak; 2. terbebas dari sikap tidak bertanggung jawab yang diakibatkan oleh pandangan bahwa nilai-nilai bukan ditimbulkan oleh kerja manusia yang muncul dari pergulatan kekuatan di masyarakat tetapi dari Tuhan yang segalanya serba jadi tanpa keterlibatan perjuangan dan kreasi manusia. Poros pertama memerdekakan manusia secara teologis, menjadikannya sebagai entitas yang berkehendak dan bertanggung jawab ; dan yang kedua memerdekakan manusia secara sosial-politis dari otoritarianisme masyarakat dan negara.
Dr. Thaha Abdurrahman, pemikir Maroko, melangkah lebih jauh. Dalam buku terbarunya, “Ruh al-Hadatsah; al-Madkhal ila Ta’sis al-Hadatsah al-Islmiyah” (2006), ia mengajukan konsep yang disebutnya dengan modernitas Islam. Konsep ini dialamatkannya kepada dua kelompok sekaligus; 1. para intelektual yang hanya mencukupkan diri dengan tradisi (turastiyyun) untuk mengajukan kepada mereka cakrawala baru, dan, 2. para intelektual modernis (hadatsiyyun) yang hanya menjadi pengikut setia modernitas barat untuk memberi mereka alternatif dari kenyataan modernitas barat yang penuh kritik.
Dr. Thaha membedakan antara “ruh modernitas” dan “kenyataan (penerapan) modernitas”. Menurutnya, modernitas barat saat ini adalah salah satu bentuk penerapan ruh modernitas yang dimungkinkan. Artinya, sangat mungkin menerapkan ruh modernitas ini di dunia Islam dalam perangkat dan bentuk yang lebih mencerminkan ruh tersebut. Tiga prinsip modernitas: prinsip kritik (mabda’ an-naqd), prinsip kearifan (mabda’ ar-rusyd) dan prinsip totalitas (mabda’ as-syumul) yang merupakan ruh modernitas dibebernya dalam bahasa dan konsep-konsep yang sepenuhnya diturunkannya dari sumber dan warisan pemikiran Islam. Pertaruhannya kemudian adalah bagaimana memperjuangkan kondisi dunia Islam yang diisi oleh perpaduan kebangkrutan intern dan luberan eksternal (modernitas barat) beranjak menuju aplikasi konsep yang dikreasinya. Setidaknya, Dr. Thaha sudah memberikan track konsepnya.
Dalam konteks perjuangan menghadapi kondisi dunia Islam yang amat berat inilah, Mohamed Abed al-Jabiri menganjurkan jalan keluar yang disebutnya “kaukus sejarah” (at-takattul at-tarikhi) dunia Arab-Islam. Kaukus ini meniscayakan umat Islam berada di satu barisan dengan garis kebijakan sosial-politik-peradaban yang dirumuskan bersama. Al-Jabiri melihat bahwa tantangan dunia Islam jauh lebih besar dari sekedar dihadapi dengan solusi-solusi sektoral. Inilah saatnya umat Islam bersatu dalam satu lingkaran untuk bergerak bangkit bersama. Solusi ini, menurut al-Jabiri, bisa mengembalikan umat Islam kembali menjadi pemain sejarah, tidak seperti kini, ketika dunia Islam menjadi obyek pertarungan (dalam apa yang disebutnya sebagai tata ulang peta dunia oleh Amerika), bukan pihak yang aktif bermain dalam pertarungan tersebut.
APAKAH peran kesejarahan ini hendak dimulai dari Jakarta melalui forum ICIS?. Melihat tren demokrasi yang mulai bersemi, kebebasan bertanggung jawab yang mulai nyata dan semangat menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, ICIS ----dengan PBNU sebagai markasnya-- bisa menjadi tonggak sejarah untuk memulai perubahan serius (kalau bukan revolusi) di dunia Islam. Asal semangatnya besar dan tujuannya jelas, ICIS bisa melakukannya. Perjuangan memang tidak pernah mengenal kata henti, bahkan mungkin baru bermula!.
Wednesday, June 14, 2006
Berkaca Dari Sepak Bola

Milyaran pasang mata, dalam sebulan ini, tertuju ke Jerman. Apa lagi, kalau bukan untuk mengikuti perhelatan empat tahunan paling menyihir: piala dunia sepak bola.
Sepak bola, di awal abad ke-21 ini, memang menjadi penyihir paling berhasil. Betapa tidak, semua unsur kepenyihiran ada disitu: uang, hiburan, kemahiran individual, gengsi, kerja kolektif, manajemen profesional, keberuntungan. Semuanya memikat. Semuanya luar biasa.
Sepak bola telah menyihir anak-anak muda dua puluhan tahun itu menjadi orang-orang kaya baru dunia. Ronaldinho, Michael Owen, Wayne Rooney adalah pesepak bola dengan kekayaan puluhan juta dolar Amerika. David Beckham, Ljunberg, telah menjadi ikon pencetak uang di dunia iklan karena bola. FIFA bakal setidaknya meraup US$1,9 milyar, hanya dari pergelaran di Jerman yang sedang berlangsung kini. Para pemain Chelsea berjudi ratusan ribu Pounsterling di satu arena balapan kuda. Roman Abramovich, orang kaya minyak Rusia itu, membeli Chelsea dan sekarang memiliki kekayaan 10 Milyar Poundsterling. Penerbangan Emirates membangun stadion Arsenal dengan US$ 700 Juta dengan perkiraan pendapatan US$ 60 juta per tahun. Pemerintah Jerman mensubsidi lebih dari US$ 1.5 milyar untuk membangun dan memperbaiki stadion yang digunakan pada piala dunia kali ini.
Iya, uang kini memang setali tiga uang dengan dunia hiburan. Sepak bola telah menjadi hiburan yang memanjakan mata milyaran orang. Lihatlah, bagaimamana Ronaldinho meliuk-liuk membawa bola bak penari samba. Lionel Messi bak penyihir cilik membawa hati berjumpalitan ketika menerobos ruang sempit pertahanan lawan. Wayne Rooney seperti roket mengejar umpan terbosan, siap menggetarkan jala lawan kapan saja. Thierry Henry dengan dingin mengecoh barisan bertahan menembus dan menembakkan bola dari sudut-sudut sempit. Masing-masing punya rasa, menjadi hiburan yang sangat menyegarkan. Orang bisa merogoh kocek ratusan euro setiap minggu demi sepak bola, demi hiburan.
Anak-anak muda hebat itu memang telah meraih segalanya; sehat, kuat, kaya, terkenal, cerdas, bersemangat dan terhormat. Tetapi apakah mereka mendapatkan itu semua secara gratis?. Tidak. Mereka bekerja keras. Semua bekerja keras: pemain, pelatih, tim teknis, manajer, direktur. Hukum peradaban bekerja disini: siapa bekerja lebih keras, ia mendapat lebih banyak. Kerja keras yang digabung dengan modal yang cukup, manajemen yang profesional, kolektifitas yang tertata rapi dan dukungan massa yang tak habis-habisnya telah melahirkan sepak bola yang kuat, indah dan memikat.
Dua tahun belakangan, kita melihat contoh kondisi ini : Chelsea di Inggris dan Barcelona di Spanyol. Masing-masing meraih gelar juara liga dua tahun berturut-turut. Barcelona, tahun ini, menambahnya dengan gelar Liga Champion. Masing-masing memperagakan sepak bola indah dengan kerjasama yang tertata bagus. Masing-masing memunclkan ikon-ikon baru di dunia sepak bola. Di Chelsea, ada Abramovich (pemodal), Jose Mourinho (pelatih) dan pemain-pemain bagus (Crespo, Drogba, Lampard, Robben, dll --wajah-wajah yang sekarang bisa kita lihat di piala dunia di tim nasional masing-masing--). Di Barcelona, ada Joan Laporta (presiden), Frank Richard dan pemain-pemain 'ciamik' (Ronaldinho, Samuel Eto'o, Henrik Larsson, Deco, Van Bomel, Lionel Messi, dst --wajah-wajah (kecuali Eto'o) yang kelihatannya bakal dominan di piala dunia ini--).
Mereka semua bisa terus bertambah cerdas karena rotasi hidup mereka yang dinamis di dunia kosmopolit. Ketika mereka bermigrasi karena bola dari negara asalnya, setidaknya mereka potensial menguasai dua bahasa, dua budaya, dua cara hidup. Ini terus bertambah ketika mereka berpindah dari klub ke klub, negara ke negara. Ditambah pula dengan pergaulan kosmopolit mereka sesama insan bola yang datang dari berbagai negara dan kebangsaan. Juninho, pemain Lyon asal Brazil dengan tendangan roket itu, begitu fasih berbahasa Perancis. Samuel Eto'o berbicara Perancis dan Spanyol. Didier Drogba, Perancis-Inggris. Ronaldo, Portugal-Italia-Spanyol. Joseph S. Blatter sendiri, Presiden FIFA, berbicara lancar dalam lima bahasa: Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol dan Italia.
Lebih dari itu, ada gengsi dan citra bangsa di sepak bola. Masih ingat dengan 'gelar kebangsawanan' David Beckam di klub-nya Real Madrid selepas menerima penghargaan langsung dari Ratu Inggris, 27/11/2003 lalu?. Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula Da Silva, (10/6), berkirim surat khusus ke Ronaldo, meminta maaf atas komentarnya soal bobot lebih Ronaldo yang diberitakan miring oleh media dan menggangu persiapan Ronaldo menghadapi piala dunia. Ratu dan pemimpin negara merasa perlu memberi penghargaan khusus kepada pahlawan sepak bola-nya karena mereka membela gengsi dan citra bangsa. Siapa yang tidak bangga ketika bendera negaranya dikibarkan dan lagu kebangsaannya dikumandangkan di tengah sorot mata milyaran manusia?. Siapa yang sekarang tidak kenal negara bernama Togo, Pantai Gading, Trinidad-Tobago setelah tim sepak bola-nya bisa lolos ke piala dunia?.
Kenyataan ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun, apalagi oleh penyelenggara negara. Itulah sebabnya, Presiden Iran, Ahmadi Nejad, merasa perlu turun ke lapangan ketika anak-anak negerinya bersiap ke piala dunia, berencana menyaksikan langsung perjuangan mereka di Jerman dan menitipkan semangat membela habis-habisan nama bangsa dan negara di lapangan hijau. Perdana Menteri Inggris, Tony Blair berjanji akan ikut tarian robot gaya Peter Crouch kalau tim kesebelasan negaranya berhasil merebut gelar piala dunia.
Sepak Bola, terbukti memang bisa menjadi lem perekat kohesi kebangsaan. Di dunia Arab pernah muncul pameo, "Arab hanya bisa disatukan oleh dua hal: Umi Kulsum, penyanyi legendaris Mesir, dan Sepak Bola". Meskipun di dunia politik, negara-negara Arab banyak 'berantem', tapi kalau ada kesebalasan negara Arab yang lolos ke even sepak bola internasional, mereka akan bersatu mendukungnya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Ketika kampanye lalu, Presiden SBY bersemboyan, "bersama kita bisa". Apakah tuan Presiden masing ingat semboyan ini ketika sekarang nonton bareng piala dunia di Istana?. Iya, sepak bola, menjasadkan semboyan ini dengan sepenuh makna kata.
Tidak ada yang jauh kalau kita bersama dan bekerja keras. Kita pasti bisa. Siapa yang awalnya menduga Togo, Pantai Gading atau Trinidad-Tobago bisa masuk piala dunia?. Tidak mustahil, kalau kita bersama dan bekerja keras, kesebelasan Indonesia bisa masuk piala dunia juga nantinya: tiga atau empat kali lagi piala dunia. Asal jelas targetnya, konsisten, didukung negara dan disemaikan dari bibit-bibit unggul yang dilatih profesional. Tidak ada keunggulan genetik dalam hal ini.
Tapi sebelum itu, iklim negara-bangsa kita harus ditata dulu. Kita bisa belajar dan berkaca dari sepak bola. Inilah saatnya segenap anak bangsa melebur dalam ruh kolektifitas dan kerja keras untuk meraih cita-cita nasional. Tanggalkan dulu kepentingan sempit dan hasrat memperkaya diri dengan mengorbankan kebersamaan. Setiap orang berusaha, berlatih, bertanggung jawab bermain cantik di posisi masing-masing.
Kita punya modal untuk itu. Alam kita, kaya. Penduduk kita, banyak. Citra kita, cukup bagus di dunia internasional. Demokrasi kita mulai bersemi. Anak-anak cerdas yang akan mengawal kreatifitas di dunia pengetahuan dan teknologi mulai merebak. Islam jalan tengah-anti kekerasan menjadi ciri khas muslim negeri ini. Tinggal kita menentukan target-target antara yang jelas dalam tenggat waktu yang tegas. Dalam lima tahun, kita raih apa. Dalam sepuluh tahun kita kejar apa. Dalam satu generasi nanti kita merebut apa. Harus jelas!.
Syarat utamanya, siapa saja yang membahayakan dan merusak permainan harus ditindak tegas tanpa ragu. Demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum. Para hakim tidak boleh ragu memberi kartu kuning atau bahkan kartu merah kepada siapapun yang merusak capaian material-spiritual bangsa kita. Hakim tidak boleh bermain mata dengan siapapun untuk merusak fair play dan spirit perjuangan. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Cobalah kita lihat, bagaimana tegasnya para wasit di piala dunia kali ini. Begitu masuk lapangan, siapapun harus tunduk pada aturan.
Akhirnya, tim atau pemain bola manapun tidak bisa mengelak dari keberuntungan. Disinilah letaknya doa. Pemain sekelas Ronaldinho sekalipun selalu berdoa selepas menjebol gawang lawan. Kerja keras habis-habisan kemudian berdoa. Semuanya akan baik. Kita bisa menjadi bangsa besar!. Jangan terlalu lama kita menunggu Indonesia Raya dan Merah Putih dikumandangkan dan dikibarkan di peristiwa-peristiwa besar di dunia ini!.
Saturday, June 03, 2006
Belajar Dari Gempa

KETIKA kita dihadapkan dengan panorama bencana: mayat-mayat berserakan, rumah-rumah runtuh, orang-orang terluka dan para pengungsi ‘kleleran’, apa yang berjumpalitan di benak kita?. Apakah yang kita rasakan?.
Sakit.
Itulah yang terjadi berulang-ulang di tanah air kita dua tahun belakangan ini: sejak gempa di Nabire, Tsunami di Aceh dan Nias, --kini—gempa di Yogyakarta dan Gunung Merapi yang masih mengeluarkan asap panas. Ketika panorama itu diputar berulang-ulang, apakah yang kita rasakan?.
Lebih sakit.
Guncangan gempa, hempasan Tsunami dan gelegak lahar itu terus-menerus menggempur hati kita, meninggalkan luka yang masih menganga. Apakah kita mesti mengeluh, “mengapa yang terus datang adalah derita demi derita, gelap di atas gelap?”.
Gelap --yang seperti pakaian-- membalut tubuh bangsa kita. Gelap yang kita sendirilah penyebab pekat dan ketakberanjakannya. Hutan-hutan kita tebangi tanpa keseimbangan; tambang-tambang kita gali habis-habisan; korupsi jadi kebanggaan; moral bangsa hanyut dibawa banjir bandang. Tindak aniaya adalah kegelapan. Demikian pesan al-Qur’an.
Akan tetapi, gelap adalah juga tempat melatih kebeningan, mempertajam perenungan dan –dengan jujur—mengakui kesalahan-kesalahan. Malam menjelang subuh adalah saat terintim manusia dengan Tuhannya.
*
LANTAS, bagaimana kita mesti belajar dari gempa?.
Kalau kita melihatnya hanyalah sekedar peristiwa alam, ilmu pengetahuan memberikan jawaban. Akal yang bekerja disini –mengutip Dr. Taha Abdurrahman, filosof Maroko-- disebut akal mulki ; akal yang menghasilkan pengetahuan.
Akal macam ini memberi kita pengetahuan bagaimana gempa bumi terjadi; bagaimana membuat sistem peringatan dini sebelum ia terjadi; bagaimana mengkonstruk bangunan tahan gempa; bagaimana menyiapkan masyarakat untuk tepat bertindak menjelang, ketika dan setelah gempa terjadi; bagaimana menyiapkan capacity building sistem penangananbencana yang kokoh-efekif ; dan seterusnya. Pemerintah dengan segala perangkat dan fasilitas yang dimilikinya paling bertanggung jawab menyediakan semua ini.
Negara-negara sekuler dan lembaga-lembaga internasional biasanya melihat bencana dari perspektif ini. Dalam konteks bencana alam, reaksi mereka bisa dirunut: ikut belasungkawa, memberi bantuan kemanusiaan (barang atau uang), memperingatkan negara korban agar membangun early warning system dan membantu negara bersangkutan untuk rekonstruksi pasca bencana. Selepas itu, kondisinya kembali ke status quo: aktivitas mereguk habis-habisan kenikmatan dunia kembali dibuka; struktur dunia yang tidak adil tetap lestari dan dunia kembali berputar dengan segala perangkat dan nilainya yang berlaku de facto.
Namun kalau kita melihat gempa dari perspektif nilai (akal malakuti), persoalannya menjadi lain. Akal macam ini mengantarkan seseorang pada keimanan. Bahwa segala peristiwa di dunia ini adalah ayat (tanda yang mengandung nilai) Allah SWT untuk mengajar manusia yang mau menggunakan kecerdasan otak dan hatinya (ulul albab).
Gempa –dalam perspektif ini—bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan alam terhadap keserakahan dan kezaliman manusia; sebagai warning system proteksi Allah SWT terhadap manusia --bahwa dengan kekuasaan-Nya manusia bisa diserang kehancuran kapan saja, oleh banjir, angin topan, gunung meletus dan lain-lain--; sebagai media untuk menguji kesabaran dan kekokohan mental sebuah komunitas untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semakin dalam perenungan dengan akal malakuti, semakin banyak makna dan kearifan yang bisa digali.
Orang beriman melihat musibah sebagai ujian. Ia akan keluar menjadi sosok yang lebih kuat setelah musibah berlalu. Kalau ia harus kembali menghadap Penciptanya sekalipun, semboyannya adalah innalillah wa inna ilahi raji’un, segalanya berasal dari Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya. Musibah yang menjadi ujian itu memberikan kesempatan kepada orang beriman untuk introspeksi; jangan-jangan ada yang salah dengan dirinya. Bisa jadi ia kurang bersyukur, kurang serius mengabdi kepada Allah, banyak melabrak larangan-larangan-Nya dan seterusnya.
Perenungan macam ini mau tidak mau akan mengantarkan sang empunya untuk kembali kepada-Nya, bertaubat, meneguhkan keimanan dan beramal saleh. Ini adalah perlajaran paling berharga yang bisa dipetik orang beriman dari bencana yang dihadapinya.
*
SIKAP mental dan perilakunya pasca bencana pasti lebih baik dari sebelumnya. Karena bisa jadi gempa adalah medium revolusi spiritual baginya untuk menapaki tangga demi tangga menuju puncak nilai keluhuran manusia.
Bisakah kita, bangsa Indonesia, belajar serius dengan mata nurani dari rentetan bencana yang menghantam negeri kita tahun-tahun belakangan ini?.
Bukankah setelah subuh, gelap pasti berlalu digantikan cahaya mentari; membuka hari baru yang cerah dan menjanjikan?. Bisakah kita merengkuhnya?.
Wednesday, May 31, 2006
Dua Doktor Baru
Hari Senin (29/5) dan Selasa (30/5) kemarin, dua putraIndonesia telah berhasil menuntaskan studi programdoktornya. Dr. Subhan Abdullah Acim (Musyarrif-CumLaude) dan Dr. M. Amar Adli (Musyarrif Jiddan-SummaCumlaude) telah 'lahir' menjadi doktor keempat dankelima dari tiga yang lebih dulu telah menuntaskanprogram yang sama: Dr. Torkis Lubis, Dr. Eka PutraWirman dan Dr. Yusuf Siddik.
Selamat untuk anda berdua. Darma bakti anda ditungguoleh masyarakat di Indonesia. Ujian yang sesungguhnyamenanti anda. Al-Muhimm ma Ba'da an-Najah, yangpenting kemudian adalah apa setelah selesai studi.Semoga Allah SWT senantiasa membimbing antum berduauntuk berbuat yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
Selamat untuk anda berdua. Darma bakti anda ditungguoleh masyarakat di Indonesia. Ujian yang sesungguhnyamenanti anda. Al-Muhimm ma Ba'da an-Najah, yangpenting kemudian adalah apa setelah selesai studi.Semoga Allah SWT senantiasa membimbing antum berduauntuk berbuat yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
Monday, May 15, 2006
Islam dan Budaya Lokal: Dialektika yang Belum Selesai

Kontroversi Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (selanjutnya disebut RUU APP) di jagat publik Indonesia membuka kembali ruang diskusi lebih serius soal kaitan antara Islam dan budaya lokal. RUU APP disinyalir sebagian kalangan sebagai kendaraan Islam untuk memberangus budaya lokal. Makna tersirat yang segera mengemuka dari kontroversi ini adalah: dialektika Islam dan budaya lokal ternyata belum selesai.
Berbeda dengan penyebaran Islam di semenanjung Arab yang revolusioner, dakwah Islam di Nusantara berlangsung dalam proses damai yang evolusioner. Penduduk Nusantara yang sudah eksis dengan agama Budha-Hindu-nya sebelum Islam datang, tidak melihat Islam sebagai ancaman bagi laku tradisi mereka. Islam tidak menyulap mereka untuk berubah 180 derajat dari apa yang mereka praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Para penyebar Islam membiarkan prilaku dan institusi budaya yang sudah hidup dan stabil itu tetap berlangsung dengan mencoba mentransformasi ruh, kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang melandasinya.
Bahkan ketika para raja tertarik dengan penampilan elegan para penyebar Islam, mereka menerima agama baru ini. Gelombang Islamisasi Nusantara pun semakin massif dan intensif. Bersamaan dengan melemahnya tiang-tiang kekuasaan kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan Islam pun bermunculan di hampir seluruh pelosok Nusantara. Dari kesultanan Aceh di barat sampai Tidore-Ternate di timur, kerajaan-kerajaan Islam membentang sepanjang Nusantara.
Panorama perkawinan Islam dengan budaya lokal ini adalah fenomena tak terbantahkan dari riwayat sejarah Islam di Nusantara. Wali Songo yang dikenal sebagai pendakwah Islam yang berhasil di Pulau Jawa memilih strategi transformasi nilai ini dengan improvisasinya masing-masing. Hasilnya, Islam mampu bertahan lama di Nusantara dalam harmoni dengan budaya lokal. Pertanyaan yang sekarang kembali mengusik: apakah strategi dan hasil yang dicapai oleh penyebar Islam awal di Nusantara adalah target sementara atau tujuan final?. Lebih menginti: apakah merubah budaya lokal pada aras nilai dan etika hanyalah sasaran antara untuk ujung-ujungnya merubahnya menjadi Islami secara isi dan kulit sekaligus?.
*
Pertanyaan ini belakangan semakin kontekstual di hadapan beberapa fenomena semisal : 1. Maraknya peraturan-peraturan daerah (PERDA) bahkan Undang-undang yang mengadopsi hukum fiqh (syariat) secara harfiah. 2. Semakin derasnya gempuran nilai dan produk budaya barat dengan latar filosofis yang berseberangan dengan nilai warisan di Nusantara. 3. Semakin kuatnya arus gerakan-gerakan Islam (harakah Islamiyah) yang semakin keras menyuarakan kewajiban Indonesia menjadi negara syariat.
Ada satu poros yang harus dibongkar terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu: SEKULARISASI. Membongkar sekularisasi di Indonesia menjadi harus untuk mengurai kesan salah bahwa seolah-olah yang berhadapan adalah Islam dengan agama atau budaya lain. Padahal senyatanya, perbenturan tersebut bisa diwakili oleh tema: perbenturan tradisi (dengan segala agama dan budaya pembentuknya) vs sekularisasi.
Akhir Agustus 2005, dalam Seminar dan Lokakarya Internasional Badan Kerjasama Perhimpunan Pelajar Indonesia (BK-PPI) Se-Timur Tengah dan Sekitarnya bertema : Membangun Masyarakat Religius di Qom Iran, terungkap bahwa dalam rentang ratusan tahun kolonialisme dan puluhan tahun pasca kemerdekaan, Indonesia telah tersekularkan hampir di seluruh level hidupnya. Satu-satunya yang belum terjadi di Indonesia adalah apa yang disebut Dr. Yudi Latif, Wakil Rektor Universitas Paramadina ---dengan mengutip Donald E. Smith-- sebagai “Polity-Dominance Secularisation”, yaitu sekularisasi yang dipaksakan oleh negara untuk merubah keyakinan, praktik dan struktur keagamaan. Selebihnya, pada bidang hukum, pendidikan, struktur sosial, ekonomi, dan –pada kadar tertentu—basis legitimasi dan identitas kelompok, semuanya telah tersekularkan.
Nusantara yang digambarkan sebaga negeri “gemah ripah loh jinawi”; negeri yang subur, makmur dan sejahtera, terus-menerus dibangkrutkan selama berabad-abad sekularisasi oleh kaum penjajah. Secara ekonomi, selain kekayaan di Nusantara dikuras dan diangkut ke luar negeri, arus perdagangan yang semula bergerak dari negeri “bawah angin” (Nusantara) ke negeri “atas angin” (Champa, China, Eropa) berbalik untuk menyisakan nusatara (selanjutnya, Indonesia) hanya menjadi sekedar penampung arus barang dari utara. Secara pendidikan, sistem madrasah yang lebih menekankan pendidikan nilai, tergantikan oleh sistem sekolahan yang beraksentuasi pada materi. Pada struktur sosial, agama “turun derajat” menjadi sekedar salah satu bagian dari fragmentasi lembaga-lembaga sosial sebagaimana terepresentasi oleh semangat lahirnya Departemen Agama. Sementara itu, hukum yang berlaku adalah hukum Belanda yang tidak sepenuhnya merepresentasi tatanan yang telah hidup berabad-abad sebelumnya dengan agama sebagai unsur utamanya.
Inilah yang menjelaskan mengapa luka bangsa Indonesia, sampai lebih dari separuh abad merdeka masih juga menganga. Bahkan sampai saat ini, bangsa Indonesia masih menjadi kuli di negeri sendiri. Kekayaan dalam negeri diangkut habis-habisan ke luar negeri. Kasus UU Migas yang hanya memberi maksimal 25 % cadangan gas untuk keperluan dalam negeri, kasus kemenangan Exxon Mobil di blok Cepu dan penggalian habis-habisan kekayaan alam Papua oleh Freeport adalah beberapa contoh mutakhir betapa ekonomi kita belum beranjak dari kerangka zaman penjajahan. Ketidakmandirian di bidang ekonomi ini berkelindan dengan ketidakmandirian di bidang politik, budaya dan pendidikan.
Ketika kondisi bangsa tidak bertambah baik secara prinsipiil dalam segala lini kehidupannya, yang terjadi kemudian adalah arus balik. Rakyat kembali membuka ingatan sejarah untuk melihat bahwa bangsa ini sudah terlalu jauh menyimpang dari keharusan sejarahnya. Rupanya segala resep sekular yang kolonialis itu tidak mampu menaikkan derajat kehidupan bangsa kita. Bahkan kecenderungan belakangan, apapun bisa masuk ke tanah air tanpa keberdayaan lembaga-lembaga negara untuk menyaringnya. Contoh terbaru adalah penerbitan majalah Playboy yang tidak bisa dihentikan oleh aparat pemerintah meskipun jelas-jelas bakal merusak moral bangsa.
Arus balik ini sebenarnya tidak khas Indonesia. Untuk menarik benang merah di aras internasional, kita bisa menyebut kasus kemenangan Partai Keadilan di Turki, kemenangan Hamas di Palestina, raihan kursi yang cukup signifikan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kekuatan menanjak Partai al-Adalah wa at-Tanmiyah di Maroko. Apalagi belakangan kita disuguhkan pemandangan menarik, bagaimana perlawanan simbolik Iran terhadap pusat-pusat kekuatan sekularisme. Intinya, sedang dan akan terus ada perlawanan terhadap pembangkrutan yang dilakukan oleh kekuatan kolonialis yang menjadikan sekularisasi sebagai salah satu alatnya.
*
Dalam buku-nya, Spirit Peradaban Islam (Ruh al-Hadlarah al-Islamiyah), Syekh Muhammad Fadil Bin Asyur, intelektual terkemuka Tunisia, mengingatkan satu jebakan yang sering tak terbaca dalam gerakan arus balik ini, yaitu : menangkap kulit dengan melupakan isi.
Misalnya, banyak orang kini ‘berteriak’ tentang solusi Khilafah Islamiyah atau penerapan Syariat Islam yang problematik itu. Padahal inti masalahnya bukan di situ. Penggerak utama peradaban Islam (sebagaimana dipraktikkan dengan sempurna pada abad pertama perluasan wilayah Islam) bukan pada bentuk khilafah, kerajaan atau keemiran, tetapi komitmen dan orientasi. Titik awal kemunduran peradaban Islam bukan terletak pada pergeseran bentuk khilafah ke bentuk kerajaan, tetapi pada perubahan dari komitmen moral-keimanan menjadi komitmen politik-kekuasaan.
Yang mesti dilakukan sekarang adalah mengembalikan komitmen pertama itu sebagai driving force gerak sejarah bangsa Indonesia kini dan ke depan. Fokus perhatian bukan terutama kepada bentuk luarnya tetapi pada substansi dan driving force-nya.
Dari perspektif ini, dialektika Islam dan budaya lokal di Indonesia akan terus berlangsung. Tidak ada yang perlu dirisaukan tentang hal itu. Biarkanlah dialektika itu menghasilkan sintesa-sintesa baru sesuai kebutuhan sejarah bangsa kita. Sekali lagi yang harus terus kita usahakan, bagaimana menjadikan rakyat dan penguasa negeri ini terus mentransformasi komitmennya dari interest keduniaan (ekonomi, politik, kekuasaan) menjadi interest keakhiratan (iman, moralitas, amal saleh, maslahah ‘ammah).
Soal bentuk, sebaiknya kita serahkan pada kecerdasan kreatifitas (ijtihad) kolektif bangsa Indonesia. Kelak, Indonesia akan maju dari usaha gigihnya sendiri. Semoga tidak terlalu lama lagi.
Saturday, April 15, 2006
Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Melihat Problem, Mencari Solusi
Mei 1998 adalah titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dari titik ini, perubahan bermula. Rezim Orde Baru (OB) yang berkuasa selama 32 tahun tumbang oleh gerakan massa. Mereka disatukan oleh sebuah tuntutan: REFORMASI.
Reformasi kemudian adalah kata kunci pada perubahan di pentas publik Indonesia. Apa yang sebelumnya tidak boleh dijamah berubah menjadi wilayah yang boleh diobrolkan secara terbuka. Wacana penerapan Syariat Islam (SI) yang di-‘tiarap’-kan pada masa OB kembali muncul ke permukaan.
Seolah memutar ulang fragmen sejarah, perdebatan tentang Piagam Jakarta kembali mengemuka di sidang umum MPR. Aceh yang menjadikan penerapan SI sebagai kartu tawar menawar politik dengan Jakarta (Pemerintah Pusat), mendapatkan kado istimewa dengan terbitnya UU Nomor 44/1999 tentang keistimewaan Aceh; sebuah undang-undang yang menandai mulainya pemberlakuan SI di Aceh. Melalui pintu otonomi daerah, banyak daerah lain yang kemudian menerbitkan peraturan-peraturan daerah (perda) yang mengadopsi SI. Belakangan, rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi (RUU APP) ditengarai sebagai perwujudan SI.
Pertanyaan yang segera mengemuka adalah : ada apa dengan gairah besar dari sebagian komponen bangsa untuk menerapkan SI di Indonesia?. Apakah SI memang jalan keluar bagi bangsa Indonesia yang didera seribu satu masalah itu? Apa problem-problem krusial bagi penerapan SI di Indonesia?. Adakah jalan keluar yang rasional dan realistis bagi kontroversi penerapan SI di Indonesia?. Pertanyan-pertanyaan yang hendak dibahas dalam tulisan ini.
Problem-problem Penerapan SI di Indonesia
Kata kontroversi adalah kata yang pas untuk mewakili wacana ini. Karena memang kontroversi penerapan SI di Indonesia terjadi di semua level. Tidak ada satu kata dalam hal ini.
Setidaknya ada dua level yang paling kentara: internal dan eksternal.
Pada level internal, menyangkut isi tubuh syariat itu sendiri, pertanyaan-pertanyaan elementer-nya adalah: apa yang dimaksud syariat dalam hal ini (ontologis)? Bagaimana merumuskan syariat yang hendak diundangkan itu (epistemologis)? Bagaimana syariat mesti diterapkan dalam konteks lokal dengan karakter yang berbeda-beda di Indonesia (aksiologis)?
Pada level ontologis, perdebatan tentang Syariat Islam sebenarnya bukan khas Indonesia. Pemikiran Arab kontemporer banyak berbicara tentang masalah ini. Persoalan poros-nya adalah: bagaimana memandang kaitan antara teks (suci: al-Qur’an, hadits dengan segala derivasi-nya) dengan realitas. Setidaknya ada tiga aliran dalam hal ini: skriptural, moderat dan liberal. Kaum skripturalis memandang bahwa realitas mesti tunduk kepada teks. Aliran moderat melihat bahwa teks dan realitas mesti berdialog untuk menghasilkan aturan yang disepakati. Sedangkan kelompok liberal melihat bahwa oleh karena teks diturunkan demi kepentingan realitas, maka ia harus menyesuaikan diri dengan realitas.
Untuk menurunkannya dalam konteks Indonesia misalnya, kita bisa mengambil beberapa contoh. 1. Kontroversi pajak sebagai zakat yang dipicu oleh buku “Agama Keadilan” yang ditulis Masdar Farid Mas’udi, sekarang salah seorang Ketua PBNU. 2. Kontroversi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digagas oleh Musdah Mulia dkk yang berimplikasi serius pada beberapa hukum keluarga semisal poligami, kawin beda agama dan nikah mut’ah. 3. Kontroversi perda pelacuran di Kabupaten Tanggerang dan yang masih hangat di wacana publik: kontroversi seputar RUU APP. Pertanyaannya adalah: manakah yang syariat dari pendapat yang berseberangan itu?.
Problem ontologis ini berkaitan erat dengan perangkat metodologis-epistemologis. Persoalan krusial disini adalah menyangkut legalitas perangkat penggalian hukum yang belakangan coba ditawarkan untuk mengakurkan teks dan realitas, semisal: perangkat takwil sebagaimana ditawarkan Nasr Hamid Abu Zayd, pendekatan Kritik Nalar yang diusulkan Mohammed Abed al-Jabiri, pembongkaran nasikh-mansukh yang dilakukan Abdullah Ahmed an-Naem, penggunaan hermeneutika-semiotika yang ditawarkan Arkoun dan seterusnya.
Tawaran-tawaran ini berangkat dari keyakinan bahwa Ushul Fiqh tidak lagi memadai untuk mengawal laju perubahan di tingkat realitas. Mengapa? Karena Ushul Fiqh ujung-ujungnya ‘betekuk lutut’ di hadapan superioritas teks. Padahal teks tidak lahir dari ruang hampa. Ia mesti berinteraksi dengan dunia manusia dengan segala pernik-perniknya. Kalau Ushul Fiqh sebagai perangkat masih tetap dianggap mumpuni oleh aliran moderat saja, mulai diragukan kapasitasnya dalam mengawal perubahan dengan produk-produk hukum yang aplikabel, bagaimana dengan mekanisme tertutup (dari teks ke teks) yang diyakini oleh kelompok skripturalis?. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa ketiga kelompok ini –dengan perangkatnya masing-masing—masih sedang bergulat dalam wacana Indonesia kontemporer. Tidakkah ini problematis?.
Lantas pada level aksiologis, syariat Islam berhadapan dengan persoalan yang tidak sederhana. Ini mengatarkan kita untuk berpindah pada sisi eksternal dari problem penerapan SI di Indonesia. Untuk mengambil beberapa sampel, kita bisa menyebut –dalam konteks ini-- : problem pluralitas-kebhinekaan Indonesia, transformasi sosial dan interaksi-belajar dengan dan dari dunia luar (negara-negara muslim dan negara-negara barat).
Pada soal pluralitas-kebhinekaan Indonesia, penerapan SI di Indonesia menghadapi tantangan serius. Masalahnya, Indonesia ditakdirkan lahir sebagai bangsa yang heterogen (warna-warni) bukan homogen (satu warna) dan itu direpresentasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi. Akibatnya, seluruh warga negara Indonesia berkedudukan dan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dari negara tanpa memandang latar belakang agama, suku dan warna kulit. Persoalan paling serius disini adalah: bagaimana penerapan syariat tidak melibas-menafikan keserbanekaan tersebut.
Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pendekatan politik-legal penerapan SI selalu mendapat tentangan, bukan hanya dari kalangan non muslim, bahkan dari kalangan tokoh-tokoh Islam sendiri. Taruhannya sangat serius yaitu eksisnya Indonesia sebagai bangsa yang kokoh bersatu. Maka, banyak tokoh atau organisasi Islam yang mengambil jalan panjang dengan transformasi sosial. Artinya, masyarakat –lewat lemba-lembaga dan nilai-nilai sosial—terus dikondisikan untuk semakin Islami. Idealismenya, tanpa pendekatan politik-kenegaraan pun kelak, rakyat Indonesia akan menjalankan syariat Islam dengan sendirinya.
Disamping itu, perlu ada dukungan internasional bagi penerapan SI di negara tertentu. Sebagaimana kita tahu, sekarang ini, Islam tengah menjadi pusat perhatian dunia. Sejak persitiwa 9/11, dunia Islam dihadapkan pada dua tantangan sekaligus: konsolidasi internal –di seluruh levelnya—dan penghadapan eksternal terutama dengan negara-negara barat (Amerika-Eropa). Di tengah tumpang tindih tata dunia yang diwarnai logika kekuatan-kekuasaan ini, penerapan syariat menjadi isu sensitif internasional. Bisakah Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim moderat, tetap bisa menjaga kredibilitasnya dalam pergaulan internasional ketika penerapan SI semakin gencar di lakukan di daerah-daerah?.
Mencari Solusi: Mencoba Lebih Maju dari Sekedar Kontroversi
Kita mulai dari satu titik berangkat (starting point) bahwa Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945-nya adalah pilihan final. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kerangka sosial-historis untuk berbicara penerapan SI di Indonesia. Penerapan SI di Indonesia tidak mungkin dimulai dari titik nol seolah-olah negara yang bernama Indonesia itu baru dimulai.
Jika titik ini disepakati, barulah kita bisa berikhtiar kreatif untuk mencari solusi bagi penerapan SI di Indonesia yang problematis itu.
Pandangan ini meniscayakan kesediaan untuk berbagi dan berkompetisi dalam berbuat kebaikan. Bahwa dalam wadah negara Indonesia, Islam hanyalah salah satu unsur pembentuk nilai-nilai, pandangan dunia dan pewarna lembaga-lembaganya. Pandangan ini pada saat yang sama tidak memberikan jawaban serba jadi bagi soal penerapan SI di Indonesia. Artinya, pendekatannya mesti induktif. Berangkat dari pemahaman yang tuntas-mendalam terhadap realitas, baru kemudian dicarikan jawaban yang match dalam khazanah syariat Islam yang kaya itu.
Kongkritnya begini: sebagai sebuah langkah gradual, tahapan teknis yang harus dilalui adalah: 1. Memahami realitas apa adanya. 2. Mencari dan mengusahakan jawaban yang sesuai dari syariat Islam. Kedua pekerjaan ini tidak mengharuskan keterlibatan negara, melaikan usaha gigih dari orang per orang dan organisasi sosial-keagamaan. Kalau boleh beranalogi dengan kasus Amerika, apa yang dilakukan oleh lembaga agama yang ujung-ujungnya melahirkan apa yang disebut barisan kanan di gedung putih, adalah contoh bagaimana lembaga agama bergerak gigih di tingkat massa untuk kemudian sampai ke ranah negara tanpa perlu pendekatan formalistik.
Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadikan tokoh dan organisasi sosial-keagamaan bisa berdialog sehat untuk secara cool ber-ijtihad menghasilkan hukum-hukum syariat (fiqh) yang match dengan kenyataan sosial lokal di Indonesia. Usaha ini akan menuntaskan persoalan ontologis dan epistemologis yang diintrodusir di atas. Ketimbang bertarung terbuka di media yang kental dengan nuansa ideologis-politis, mengapa mereka tidak duduk bersama di ruang ber-AC untuk membicarakan hukum-hukum SI yang klop dengan kondisi dimana ia mesti diterapkan dan dengan cara bagaiamana ia mesti diperjuangkan?.
Sementara itu, pada level eksternal, tranformasi sosial yang sudah dilakukan, misalnya oleh NU sejak 1984, perlu terus dilakukan dengan kualitas yang terus ditingkatkan. Langkah ini selanjutnya dikemas dengan wacana yang santun, anti kekerasan, dialogis dan mengedepankan rahmat. Ketika terbukti di bumi realitas bahwa Islam betul-betul menjadi rahmat bagi semua, tanpa diformalkan sekalipun, Islam akan menjadi nilai obyektif di tengah masyarakat. Dalam khazanah klasik, pandangan seperti ini, misalnya kita temukan pada visi politik Imam Malik yang belakangan mazhab fiqh-nya lebih memungkinkan akrab dengan tradisi lokal dengan konsep mashlahah mursalah dan maqashid syariah-nya.
Selanjutnya kesediaan untuk tunduk pada aturan main bersama (rule of the game) pada saat kekuatan umat Islam telah menjelma menjadi entitas politik berupa partai-partai harus terus dipupuk dalam semangat menyemaikan demokrasi. Sebab terbukti bahwa demokrasi sebagai perangkat bernegara tidak kontradiktif dengan Islam. Dan akhirnya, tetap perlu digalang konsolidasi global antar negara dan komunitas muslim untuk mewujudkan tata dunia yang lebih adil dan damai.
Semua tawaran aksi ini, sama sekali bukan jawaban jadi. Kerja keras dalam mewujudkannya akan menentukan masa depan Indonesia. Satu hal yang penting kita tegaskan: ketimbang energi bangsa kita habis untuk ‘bertengkar’ dalam soal-soal yang tidak perlu, mengapa kita tidak membicarakan sesuatu yang dalam jangka panjang lebih menjamin kohesi kebangsaan, kebanggaan menjadi sebuah bangsa dan capaian-capaian riil pada pembangunan benda maupun manusianya. Bukankah seluruh elemen bangsa dengan segala pelangi ideologi dan jalan hidupnya berujung pada muara menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, damai, adil dan sejahtera?.
Tinggal kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing: apakah yang bisa kita sumbangkan dalam kerja besar ini?. Kita sendirilah yang bisa menjawabnya dengan kerja nyata.
Reformasi kemudian adalah kata kunci pada perubahan di pentas publik Indonesia. Apa yang sebelumnya tidak boleh dijamah berubah menjadi wilayah yang boleh diobrolkan secara terbuka. Wacana penerapan Syariat Islam (SI) yang di-‘tiarap’-kan pada masa OB kembali muncul ke permukaan.
Seolah memutar ulang fragmen sejarah, perdebatan tentang Piagam Jakarta kembali mengemuka di sidang umum MPR. Aceh yang menjadikan penerapan SI sebagai kartu tawar menawar politik dengan Jakarta (Pemerintah Pusat), mendapatkan kado istimewa dengan terbitnya UU Nomor 44/1999 tentang keistimewaan Aceh; sebuah undang-undang yang menandai mulainya pemberlakuan SI di Aceh. Melalui pintu otonomi daerah, banyak daerah lain yang kemudian menerbitkan peraturan-peraturan daerah (perda) yang mengadopsi SI. Belakangan, rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi (RUU APP) ditengarai sebagai perwujudan SI.
Pertanyaan yang segera mengemuka adalah : ada apa dengan gairah besar dari sebagian komponen bangsa untuk menerapkan SI di Indonesia?. Apakah SI memang jalan keluar bagi bangsa Indonesia yang didera seribu satu masalah itu? Apa problem-problem krusial bagi penerapan SI di Indonesia?. Adakah jalan keluar yang rasional dan realistis bagi kontroversi penerapan SI di Indonesia?. Pertanyan-pertanyaan yang hendak dibahas dalam tulisan ini.
Problem-problem Penerapan SI di Indonesia
Kata kontroversi adalah kata yang pas untuk mewakili wacana ini. Karena memang kontroversi penerapan SI di Indonesia terjadi di semua level. Tidak ada satu kata dalam hal ini.
Setidaknya ada dua level yang paling kentara: internal dan eksternal.
Pada level internal, menyangkut isi tubuh syariat itu sendiri, pertanyaan-pertanyaan elementer-nya adalah: apa yang dimaksud syariat dalam hal ini (ontologis)? Bagaimana merumuskan syariat yang hendak diundangkan itu (epistemologis)? Bagaimana syariat mesti diterapkan dalam konteks lokal dengan karakter yang berbeda-beda di Indonesia (aksiologis)?
Pada level ontologis, perdebatan tentang Syariat Islam sebenarnya bukan khas Indonesia. Pemikiran Arab kontemporer banyak berbicara tentang masalah ini. Persoalan poros-nya adalah: bagaimana memandang kaitan antara teks (suci: al-Qur’an, hadits dengan segala derivasi-nya) dengan realitas. Setidaknya ada tiga aliran dalam hal ini: skriptural, moderat dan liberal. Kaum skripturalis memandang bahwa realitas mesti tunduk kepada teks. Aliran moderat melihat bahwa teks dan realitas mesti berdialog untuk menghasilkan aturan yang disepakati. Sedangkan kelompok liberal melihat bahwa oleh karena teks diturunkan demi kepentingan realitas, maka ia harus menyesuaikan diri dengan realitas.
Untuk menurunkannya dalam konteks Indonesia misalnya, kita bisa mengambil beberapa contoh. 1. Kontroversi pajak sebagai zakat yang dipicu oleh buku “Agama Keadilan” yang ditulis Masdar Farid Mas’udi, sekarang salah seorang Ketua PBNU. 2. Kontroversi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digagas oleh Musdah Mulia dkk yang berimplikasi serius pada beberapa hukum keluarga semisal poligami, kawin beda agama dan nikah mut’ah. 3. Kontroversi perda pelacuran di Kabupaten Tanggerang dan yang masih hangat di wacana publik: kontroversi seputar RUU APP. Pertanyaannya adalah: manakah yang syariat dari pendapat yang berseberangan itu?.
Problem ontologis ini berkaitan erat dengan perangkat metodologis-epistemologis. Persoalan krusial disini adalah menyangkut legalitas perangkat penggalian hukum yang belakangan coba ditawarkan untuk mengakurkan teks dan realitas, semisal: perangkat takwil sebagaimana ditawarkan Nasr Hamid Abu Zayd, pendekatan Kritik Nalar yang diusulkan Mohammed Abed al-Jabiri, pembongkaran nasikh-mansukh yang dilakukan Abdullah Ahmed an-Naem, penggunaan hermeneutika-semiotika yang ditawarkan Arkoun dan seterusnya.
Tawaran-tawaran ini berangkat dari keyakinan bahwa Ushul Fiqh tidak lagi memadai untuk mengawal laju perubahan di tingkat realitas. Mengapa? Karena Ushul Fiqh ujung-ujungnya ‘betekuk lutut’ di hadapan superioritas teks. Padahal teks tidak lahir dari ruang hampa. Ia mesti berinteraksi dengan dunia manusia dengan segala pernik-perniknya. Kalau Ushul Fiqh sebagai perangkat masih tetap dianggap mumpuni oleh aliran moderat saja, mulai diragukan kapasitasnya dalam mengawal perubahan dengan produk-produk hukum yang aplikabel, bagaimana dengan mekanisme tertutup (dari teks ke teks) yang diyakini oleh kelompok skripturalis?. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa ketiga kelompok ini –dengan perangkatnya masing-masing—masih sedang bergulat dalam wacana Indonesia kontemporer. Tidakkah ini problematis?.
Lantas pada level aksiologis, syariat Islam berhadapan dengan persoalan yang tidak sederhana. Ini mengatarkan kita untuk berpindah pada sisi eksternal dari problem penerapan SI di Indonesia. Untuk mengambil beberapa sampel, kita bisa menyebut –dalam konteks ini-- : problem pluralitas-kebhinekaan Indonesia, transformasi sosial dan interaksi-belajar dengan dan dari dunia luar (negara-negara muslim dan negara-negara barat).
Pada soal pluralitas-kebhinekaan Indonesia, penerapan SI di Indonesia menghadapi tantangan serius. Masalahnya, Indonesia ditakdirkan lahir sebagai bangsa yang heterogen (warna-warni) bukan homogen (satu warna) dan itu direpresentasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi. Akibatnya, seluruh warga negara Indonesia berkedudukan dan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dari negara tanpa memandang latar belakang agama, suku dan warna kulit. Persoalan paling serius disini adalah: bagaimana penerapan syariat tidak melibas-menafikan keserbanekaan tersebut.
Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pendekatan politik-legal penerapan SI selalu mendapat tentangan, bukan hanya dari kalangan non muslim, bahkan dari kalangan tokoh-tokoh Islam sendiri. Taruhannya sangat serius yaitu eksisnya Indonesia sebagai bangsa yang kokoh bersatu. Maka, banyak tokoh atau organisasi Islam yang mengambil jalan panjang dengan transformasi sosial. Artinya, masyarakat –lewat lemba-lembaga dan nilai-nilai sosial—terus dikondisikan untuk semakin Islami. Idealismenya, tanpa pendekatan politik-kenegaraan pun kelak, rakyat Indonesia akan menjalankan syariat Islam dengan sendirinya.
Disamping itu, perlu ada dukungan internasional bagi penerapan SI di negara tertentu. Sebagaimana kita tahu, sekarang ini, Islam tengah menjadi pusat perhatian dunia. Sejak persitiwa 9/11, dunia Islam dihadapkan pada dua tantangan sekaligus: konsolidasi internal –di seluruh levelnya—dan penghadapan eksternal terutama dengan negara-negara barat (Amerika-Eropa). Di tengah tumpang tindih tata dunia yang diwarnai logika kekuatan-kekuasaan ini, penerapan syariat menjadi isu sensitif internasional. Bisakah Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim moderat, tetap bisa menjaga kredibilitasnya dalam pergaulan internasional ketika penerapan SI semakin gencar di lakukan di daerah-daerah?.
Mencari Solusi: Mencoba Lebih Maju dari Sekedar Kontroversi
Kita mulai dari satu titik berangkat (starting point) bahwa Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945-nya adalah pilihan final. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kerangka sosial-historis untuk berbicara penerapan SI di Indonesia. Penerapan SI di Indonesia tidak mungkin dimulai dari titik nol seolah-olah negara yang bernama Indonesia itu baru dimulai.
Jika titik ini disepakati, barulah kita bisa berikhtiar kreatif untuk mencari solusi bagi penerapan SI di Indonesia yang problematis itu.
Pandangan ini meniscayakan kesediaan untuk berbagi dan berkompetisi dalam berbuat kebaikan. Bahwa dalam wadah negara Indonesia, Islam hanyalah salah satu unsur pembentuk nilai-nilai, pandangan dunia dan pewarna lembaga-lembaganya. Pandangan ini pada saat yang sama tidak memberikan jawaban serba jadi bagi soal penerapan SI di Indonesia. Artinya, pendekatannya mesti induktif. Berangkat dari pemahaman yang tuntas-mendalam terhadap realitas, baru kemudian dicarikan jawaban yang match dalam khazanah syariat Islam yang kaya itu.
Kongkritnya begini: sebagai sebuah langkah gradual, tahapan teknis yang harus dilalui adalah: 1. Memahami realitas apa adanya. 2. Mencari dan mengusahakan jawaban yang sesuai dari syariat Islam. Kedua pekerjaan ini tidak mengharuskan keterlibatan negara, melaikan usaha gigih dari orang per orang dan organisasi sosial-keagamaan. Kalau boleh beranalogi dengan kasus Amerika, apa yang dilakukan oleh lembaga agama yang ujung-ujungnya melahirkan apa yang disebut barisan kanan di gedung putih, adalah contoh bagaimana lembaga agama bergerak gigih di tingkat massa untuk kemudian sampai ke ranah negara tanpa perlu pendekatan formalistik.
Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadikan tokoh dan organisasi sosial-keagamaan bisa berdialog sehat untuk secara cool ber-ijtihad menghasilkan hukum-hukum syariat (fiqh) yang match dengan kenyataan sosial lokal di Indonesia. Usaha ini akan menuntaskan persoalan ontologis dan epistemologis yang diintrodusir di atas. Ketimbang bertarung terbuka di media yang kental dengan nuansa ideologis-politis, mengapa mereka tidak duduk bersama di ruang ber-AC untuk membicarakan hukum-hukum SI yang klop dengan kondisi dimana ia mesti diterapkan dan dengan cara bagaiamana ia mesti diperjuangkan?.
Sementara itu, pada level eksternal, tranformasi sosial yang sudah dilakukan, misalnya oleh NU sejak 1984, perlu terus dilakukan dengan kualitas yang terus ditingkatkan. Langkah ini selanjutnya dikemas dengan wacana yang santun, anti kekerasan, dialogis dan mengedepankan rahmat. Ketika terbukti di bumi realitas bahwa Islam betul-betul menjadi rahmat bagi semua, tanpa diformalkan sekalipun, Islam akan menjadi nilai obyektif di tengah masyarakat. Dalam khazanah klasik, pandangan seperti ini, misalnya kita temukan pada visi politik Imam Malik yang belakangan mazhab fiqh-nya lebih memungkinkan akrab dengan tradisi lokal dengan konsep mashlahah mursalah dan maqashid syariah-nya.
Selanjutnya kesediaan untuk tunduk pada aturan main bersama (rule of the game) pada saat kekuatan umat Islam telah menjelma menjadi entitas politik berupa partai-partai harus terus dipupuk dalam semangat menyemaikan demokrasi. Sebab terbukti bahwa demokrasi sebagai perangkat bernegara tidak kontradiktif dengan Islam. Dan akhirnya, tetap perlu digalang konsolidasi global antar negara dan komunitas muslim untuk mewujudkan tata dunia yang lebih adil dan damai.
Semua tawaran aksi ini, sama sekali bukan jawaban jadi. Kerja keras dalam mewujudkannya akan menentukan masa depan Indonesia. Satu hal yang penting kita tegaskan: ketimbang energi bangsa kita habis untuk ‘bertengkar’ dalam soal-soal yang tidak perlu, mengapa kita tidak membicarakan sesuatu yang dalam jangka panjang lebih menjamin kohesi kebangsaan, kebanggaan menjadi sebuah bangsa dan capaian-capaian riil pada pembangunan benda maupun manusianya. Bukankah seluruh elemen bangsa dengan segala pelangi ideologi dan jalan hidupnya berujung pada muara menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, damai, adil dan sejahtera?.
Tinggal kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing: apakah yang bisa kita sumbangkan dalam kerja besar ini?. Kita sendirilah yang bisa menjawabnya dengan kerja nyata.
Saturday, February 11, 2006
Hajj: An Impressing Experience
Every time you visit Makkah to pilgrim and Madinah to visit Holy Prophet Mosque, you'll feel that you want to do that more and more...
I believe that you'll find something new, every time you do that: new horizon that enrich your life. At this hajj season, I got a deeper understanding about spirituality, vitality, collectivity and equality that Islam teach in this worship.
I'll tell you the stories about this values in the next postings...
I believe that you'll find something new, every time you do that: new horizon that enrich your life. At this hajj season, I got a deeper understanding about spirituality, vitality, collectivity and equality that Islam teach in this worship.
I'll tell you the stories about this values in the next postings...
Sunday, February 05, 2006
I'm Coming Back
When we deal with so much works with very little time, we automatically think about priority. That is what I deal with in these previous days. Working as translater in Makkah Office of Indonesian Hajj Mission, I must spend most of my time in front of computer translating articles, news, letters, reports etc from Arabic/English to Bahasa Indonesia or from Bahasa Indonesia to Arabic/Engllish. So, It is not easy to find condusive circumstance to blog. But now, something is going to be normal. Insya Allah, in the next days, I will post frequently as usual.
There were so much interesting experiences I found during this Hajj season. I'll tell the stories one by one, Insya Allah.
There were so much interesting experiences I found during this Hajj season. I'll tell the stories one by one, Insya Allah.
Subscribe to:
Comments (Atom)